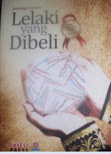24 Desember 2009
Bulan di Tungku Ibu
ia menanak doa-doa juga air mata
saat bocah-bocah menahan perih di lambungnya
siang ini teramat terik untuk menangis
sedang gerimis di dapurku
adalah rintik tak habis-habis
mencipta lautan dan kerinduan tentang ombak
tempat bocah-bocah pantai berlayar dan menjaring bulan
tapi yang tersisa hanya ikan
dan tulang belulang bapak-bapak mereka
bulan telah matang di tungku ibu,
di nyeri nyilu lambungku
Semarang, 23 Desember 2009
9 Desember 2009
Ibrahim
seperti dulu
kau cecap api
dari sebilah kapak
yang tak tuntas
menebas
leher-leher berhala
dan kau kalungkan di nasib anakmu juga
cepatlah tebas
dan langit yang menampung air matamu
sempat mengajari anak itu
mengeja nama Tuhanmu
hingga nasibmu tak seperti nasib bapakmu
dan mata air mengucur lewat kakinya
itulah air mataku yang tak kunjung tahu
bagaimana merapal doa
sedang denyut waktu makin membuat kita alpha
dan kapakmu itu kelak mampir juga di urat-urat leherku
adakah waktu yang sama-sama kita kuliti?
sampai benar-benar habis aku
di riak-riak ayat terakhir yang kau baca
Semarang, 28/11/09
2 November 2009
Malioboro, Saat Subuh Hampir Habis
sudut kota
monumen atas nama sejarah
terukir lewat tinta darah
dan pada perjalananlah
kita terlempar di sini
malioboro
aku kembali
di lindap pendar lampu
dan malam menggeliat di atas bangku
sebelum khatam kugenapi riwayat
kisah tapak kakiku yang berkarat
orang-orang dengan wajah memucat
menyapa dalam tatap jarak keasingan
kamilah kini yang memendam kesumat
malioboro
di sudut wajahmu pernah kucatat
di sinilah peziarah tumpah rindunya
dan kami kembali menggenapi sepi
dalam sorak dan luka
tapi wajahmu itu tetap saja sunyi
kukuliti di sudut sepi
Jogjakarta, 01/11/09
30 Oktober 2009
Sketsa Wanita Bermata Kaca
pecahan-pecahan kaca
menjadi serupa
matamu
Entah sampai huruf ke berapa telah kuulang tiap percakapan. sampai rindu memang benar-benar selesai. Kau telah mampu menghentikan tangis dan matamu mengisyaratkan malam retak dengan sepi yang menggait punggung kita tiba-tiba, sampai harus saling lekat dan ku sandarkan kepalaku di kepalamu.
Seperti apa sebuah perjalanan telah melaju atas nama kita? dan gaib hanya kita sepakati dengan anggukan dan air mata. Di matamu, pernah dulu aku berkaca. Melihat tubuhku sepotong-sepotong. Tanganku, dadaku, punggungku, kepalaku lalu kau susun rapi menjadi utuh. Dan kukenakan kembali tubuh yang rapuh. Matamu itukah yang mengisyaratkat waktu berhenti dan detak jantungku seperti habis dilumat sepi?
Percakapan kita memang sampai karena memang harus kita akhiri dan matamu yang dulu kaca, retak dalam malam yang kian buta, berkaca-kaca. Dan kau kembali berjalan dengan mengemasi rindu yang selesai tiba-tiba. Simpanlah barangkali menjadi peta menuju kampung yang lelah menunggu kepulanganmu, atau larungkanlah ke sungai biar hilir menggenapi segala gaib yang mengait nama kita yang ganjil dan namaku sampai juga ke muara, semoga.
Kini kubiarkan kau berjalan dengan mimpi yang kau tepis. Bahkan sejak mula aku tahu kau takut merindukanku, maka kau tulis saja namaku di tanah biar disapu angin yang resah. Tapi aku berbelok dengan masih mengenangmu karena perjalanan takkan mampu dicuri lewat apapun. Dan aku tak takut menjadi orang yang kehilangan. Karena begitulah semestinya hidup. Di garis-garis tangan, tersusun samar sketsa wajah yang patah. Dan pecahan kaca dari matamu ku simpan di saku baju, barang kali kelak aku jatuh dan merindukan lagi tatap matamu.
Semarang, 30/10/09
26 Oktober 2009
Gerbang Kota
adalah waktu yang rapat
dan debu-debu sesat di pelupuk mata
jalanan memucat
lewat senja dengan garis sewarna jelaga
di atas trotoar
orang-orang memangkas nasib
sebagian tertawa
sebagian memicing mata
Tiang penyangga dari batu dan baja
kian berkarat dan melayu
tak habis mencatat
usia waktu
Semarang, 26/10/2009
21 Oktober 2009
Peta di Kolong Ranjang
sunyi dan kita lebih menerima bahwa kita memang sendiri
biar cahaya menyeruak di ranjang dan bantal
aku tak perduli jika luka makin mengental
aku ingin tidur di kolong ranjang saja
memintal benang-benang sepi
menjadi peta menuju kotamu
yang kerap ku kunjungi dalam mimpi
Semarang, 19 oktober 2009
3 Oktober 2009
Sajak Tanah Patah
seperti tubuh kami
dalam kedukaan
padang, pariaman
seperti apa isyarat harus merupa dalam ingatan
sedang segala laju musim takkan pernah mampu kita ramalkan
maka sekali lagi ku sebut namamu
dalam rapal-rapal yang kadang tak kami tahu
terduduk
dengan jari menunjuk
langit sepi
segala menepi di batas waktu
kita khatam berdoa
selesai ayat luka
Jika sajak-sajak adalah doa
ku harap sampai
dan aku terima
riwayat lepas merupa sakit
wajah kamilah yang sakit
dalam kedukaan
padang, pariaman.
Semarang, 03/10/09
2 Oktober 2009
Sketsa Belati Patah
Biarlah sajalah, dadamu kau busungkan, sedang doa yang ku kirim demi mengisi kedukaan hanya mengalir dan jatuh di alas kakimu. Tapi ku kira kita memang hanya perlu bersapa, tanpa perlu banyak mereka-reka, karena aku akan lebih merasa kecewa. Pengharapan kadang membuat kita berlebihan. Saat kau kirim sajak-sajak bising, ingin sekali ku tebas lehernya dan tak kan ada darah yang mengalir. Karena hanya kosong dan kau tak pernah belajar mengosongkan. Selain mengisi dan selalu kutukan sebagai isyarat, kau belum pernah ke mana-mana selain dendam yang purba.
Kini biarlah aku berpaling dari rindu yang kau tawarkan. Sungguh aku takut membencimu atas nama belati yang selalu kau kirim setiap pagi. Karena kelak ia pasti tertancap dan patah di dadamu sendiri. Dan itu sakit sekali. "Kau masih takut bukan?"
Saat itu kau akan tahu betapa bebal sejenak perjalanan. Dan kita bukan apa-apa di setapak jalan.
Semarang, 02/10/09
24 September 2009
Sebuah Jalan dan Nama di Tubuh Daun
deru-deru dari nasib waktu
melumat kita,
menjadi serupa debu
bulan menepi di kaca-kaca matamu
aku mendo'a untuk sempat memotongnya
menjadi sabit
yang menetak tubuhku satu persatu
aku menghitung bilangan ganjil
dan mereka-reka kembali ingatan
pada gaib
yang menyekutukan kita
dan melarikan sunyi di kantong-kantong mata
sesekali aku melihatmu di sisi jendela
kau masih berdiri tanpa menoleh sedikitpun
menjabat angin yg resah menyibak daun
dan meruntuhkannya saat hari makin matang
menghitung satu-satu yang gugur
"adakah namaku di tubuh daun?"
Solo, 21/09/09
15 September 2009
Subuh Dalam Denging yang Tak Selesai
kita tergesa mengeja kalimat
dan gema yang terlempar dari ranah sepi itu
kini berdenging dan menyesak di dadamu
penuh
tubuh kita meluruh
sebilah kapak ibrahim kau kalungkan di leherku
dan tongkat musa telah kau lempar ke muara batu
tepat saat subuh menetak lidahku
yang terbata mengeja namamu
Semarang, 13/09/09
Sketsa Daun Pintu
Kau sendiri yang memaksaku sebelum kau tak mampu melepasku. Aku pergi karena memang kau harus sendiri. Memintal doa-doa di sudut sepi. Air matamu yang deras bermuara di muka pintu. Memanggilku untuk kembali.
Sudahlah, pintumu memang telah patah di tubuh angin yang sama sekali tidak pernah kita panggil, dan kau terus menambalnya dengan air mata. Bersyukurlah kita masih bisa menangis.
Rindu memang memilih ujungnya sendiri. Pintu itu juga telah memilih tamunya sendiri. Kau tinggal duduk dan memulai percakapan. Aku tak peduli jika sesabit bulan yang lama kau eram telah memutus pergelangan tanganku saat ku genggam tanganmu.
Pintu itu pula yang melempar kita pada ranah yang sama. Di kota penuh kutuk. Kita juga di kutuk. Menjadi angin yang tak tahu sarangnya. Hanya berpusing di tanah tandus dan mengirimkan debu di mata para musafir. Mencium punggung daun, menarik-narik tangkainya, lalu putus.
Setidaknya kita tidak jadi badai yang mengangkat atap dan doa-doa ke langit itu, yang ketika sampai di sana segalanya hanya akan terbakar. Karena beribu-ribu malaikat penjaga takkan sudi pelataran rumahNya di masuki begitu saja, kecuali tamu yang memang telah di tunggu.
Dan itu bukan kita.
Aku ingin tertawa sekarang. Aku juga melihatmu tersenyum lepas. Kenapa dulu aku tak memaksa untuk tinggal. Menanggalkan segala kecurigaan. Membiarkan sabit itu memotong-motong tubuhku yang lain. Sedang aku tahu telapak tanganku masih kau genggam. dan kita bertemu kembali untuk menghitung sisa-sisa percakapan.
"aku mencuri tanganmu" katamu.
"aku mematahkan daun pintumu"
"Sialan!"
Memang! Sekarang aku hanya berharap dapat mencium bahumu diam-diam, dan saat kau palingkan tubuhmu aku telah menghilang. Bersama angin yang menunggu di depan pagar. Menjadi kedukaan yang kau tenun rapi dalam ingatan.
Aku tahu tak ada orang lain yang kau biarkan masuk, walau banyak yang mengetuk. Selain aku, dulu. Terima kasih sayang.
Sekalah air matamu dan tahanlah tangismu. Pintu itu akan membuka dan memilih tamunya sendiri. Kau tinggal duduk dan mengulang percakapan.
Semarang, 14/09/09
5 September 2009
Sketsa Kelopak Mata dengan Pendar Cahaya Bulan
Kau pasti telah tahu lebih dulu, bahwa percakapan kita pasti selesai. Maka kau biarkan aku datang dan secangkir teh hangat telah lama kau siapkan. Kadang kelu juga lidahku, karena kau memang lebih memilih menjalani perdebatan dengan segala yang mengabu. Sampai sepi pun harus kita habisi saat maghrib terlampau cepat datang, waktunya aku pulang dengan senyum kecil, dan sebait rindu selesai juga kita tuntaskan. Sudut matamu bercahaya, serupa rahim kunang-kunang yang dari sana memancarkan pendar cahaya temaram. Sewarna bulan yang matang, kini bulan itu jatuh tepat di sudut matamu. Sungguh kelak pastilah aku merindukanmu. Walau tanpa percakapan yang panjang, sunyi dengan segala yang diam.
Maka lelaplah kita saat setengah bayang bulan jatuh di tiang keranda. ah,, matamu, sajak-sajakku tersesat di sana, lemparlah kembali dan kirim ke muaranya. Seperti saat kita kenangkan duka lalu nafas kita yang panjang melepaskan segalanya.
Lelaplah lelap dan katupkan matamu lewat doa-doa yang tersesat di tepi ranjang kita. Dan selesaikanlah kau tenun duka-duka, karena aku takut mengelus pipimu yang merah masak, juga ku kirim sunyi ke lubang telingamu. Hingga tak ada suara lain yang kau dengar selain denging dan detak jantungmu sendiri.
kadang menyebut namamu,
kadang menyebut namaku,
kadang tak siapa-siapa,,,
Lelaplah lelap dan habisi segala duka lewat kelopak matamu.
Kita memang mudah kalah dan rela di habisi,
tapi kita belum selesai bukan?
Ku cium keningmu dalam pendar bulan, juga sajak-sajak yang tanggal.

Semarang, 05/09/09
24 Juli 2009
Sketsa Batu Sungai

Aku tahu kau akan menangis. Aku tahu kau akan menepis. Inilah jejak batu yang mengendap di sungai. Arus-arus melumat tapi kekal jejakku selalu tertanam. Ah, pasanglah matamu di tempatnya, hingga kau benar-benar terjaga. Tapi berhentilah mencurigai, karna picing-picing mata hanya mengarah serapah, karna ratap anak-anak sungai akan sampai ke muara.
Kau tahu? Malam tidak benar-benar buta. Sunyi-sunyi merapat di kolong ranjang kita. Dan kau akan mengumpati bayangmu sendiri. Yang lindap dan sesat. Sampai gigil lebih terpahami saat kau sendiri. Dan aku memang lebih memilih serupa batu. Karna darah memang darah. Karna tanah memang tanah. Karna kalah memang kalah. Sederhana,,,
Oh,.. akulah kekal batu menjejal di aorta dan nadimu. Berdegup dan menepi di sudut. Memilih tak bermuara biar deras-deras arus lumat-melumat nama-nama. Mengendap terlampau purba dan waktu hanya membuat kita sia-sia. Aku kikis, kikis menipis. Kau sampai, sampai tiada.
Pulang atau pergi sederhana.
Eloprogo, 19/07/09 01:25
22 Juli 2009
Sketsa Sungai

Sebentang jejak-jejak bebunga, sepagi ini tepi jalan adalah waktu yang rimbun, daun-daun berserak, bunga-bunga tergeletak, terinjak-injak. Orang-orang berkisah tentang kegilaan mereka.
Potongan daun-daun telinga yang di tabur sepanjang jalan tadi sempat ku pungut satu dan ku simpan di saku.
Sampai di ujung aku memilih membuang muka, pada sungai. “aku masih sempat melihatmu tersenyum”, tapi telah ku larutkan segalanya di sini. Sketsa sungai dengan dua arus bertempur. Para leluhur melempar tubuhnya, memilih hanyut. Kita seperti mereka. Tersesat dan harus meratap.
Sepotong telinga yang tadi ku pungut, ku buang dan ku biarkan hanyut. Sungai akan mengantarmu pada muara yang tepat.
Eloprogo, 17/07/09
15 Juli 2009
Seikat Janji, Darah dan Sesloki Arak
Lewat percakapan yang diam
dan tangis yang kita rapal
Darah memang lebih berarti
dari sekedar percakapan basi
Maka cukuplah kita ikat selembar janji
Lewat sesloki arak
dan atas nama Tuhan yang maha bijak
Sunyi yang kita ratap di mata badik
Lebih lindap dari segala sorak
Semarang, 20/06/09. 00:15
4 Juni 2009
Secangkir Kopi dan Puisi
Tentang reranting kering, gerimis juga secangkir kopi
Kita berdebat tentang kabut
Mimpi-mimpi yang lenyap bersama kepul asap di tungku
Kurebus kenangan di dadamu
Matahari tak mampir di sini
Hanya menetap di keningmu
Lalu mati
Kita tenggelam dalam keremangan
“Kau lihat?”
Begitu senyap kita mengeja
Perbincangan kita takkan usai
Secangkir kopi di lidah pagi
Lebih manis dari puisi
Semarang, kampus sastra 28/10/08
29 April 2009
Sepotong Janji Untuk Kekasih
Dalam temaram lampu yang likat
Lewat bisik sunyi yang lindap
Kapal-kapal telah berlabuh
Di ujung kakimu
Aku luluh
Serupa mantra dalam dupa
Doa-doa bermuara juga
Langit teduh
Namamu ku ikat dalam janji
Di rumah kita yang gaduh
Semarang, 20/04/09
15 April 2009
Patung Kamajaya
Menetes pada tubuh angin
Menyeruk pada malam yang bisu
Di atas tanah telah bermuara nama-nama
Seperti kilatan yang patah
Di ujung kakimu
Lalu segalanya menjadi rindu yang tak sekedar
Malam berkabut
Kunang-kunang di garis matamu
Nama-nama yang lupa ku sebut
Lalu tanah muara tangismu
Kunang-kunangmu ku curi
Ku bawa lari
Kau masih berandai-andai dengan mimpi
Menjadi kekasih dari gadismu
Lalu kau serupa batu sejak itu
Kini aku yang mencurimu
Ku kunci kau di laci almari
Dengan patung gadismu

Semarang, 28/03/09
Sebuah Catatan Yang Terpaksa Ku Catat

Di bawah lampu kota, keriput garis keningmu kian melayu pada cahaya
Sebelum hujan
Memang harus ada yang diselesaikan
Dan tubuhmu yang menajam
Kian menyabit segala kerinduan
Tentang rumah
Juga pagi hari yang ramah
Ibu yang membakar doa di tungku
Juga sebuah pintu, menjadi awal persinggahan yang tamak melemparmu
Ke padang-padang rumput, juga alamat-alamat nisbi
Tapi segalanya memang terlampau berlebihan
Seperti dirimu di ruas-ruas jari yang layu
Seperti diriku yang selalu terpaksa mencatat riwayat kepulanganmu
Semarang, 29/03/09
1 April 2009
Purnama di Mata Anak-Anak

Dari luka yang nganga
Orang-orang berpaling dan membuang segala doa
Langit yang rimbun di atas kota
Mangabarkan cuaca teramat darah
Anak-anak mambaca bait-bait yang sunyi
Dari kulit bulan yang lebih layu dari sepi
Saat purnama
Bulan di di mata mereka
Anak-anak mengantongi bola-bola
Bulan-bulan adalah kelereng dalam mimpi
Mari bertaruh, mana yang lebih luka dari bising dan sunyi?
Maka tak ada yang pantas dirindukan kini
Selain kelereng
Dan mimpi
Semarang, 23/03/09
foto di ambil di http://arydwantara.wordpress.com
27 Maret 2009
Sepotong Bulan dan Langit Untuk Lelaki

Sepotong bulan di bawah lampu
Dan langit yang rindu
Lelaki menggenggam belati dan mengumpati puisi-puisi basi
Dari tangannya bulan perak adalah kembang bambu
Juga gang-gang sepi beralamat langit yang pasi
Mari mengutuki mimpi
Juga kalimat-kalimat bohong
Mulutmu kosong?
Ah dasar omong kosong
Hati perawan di sakunya
Bulan perak,… Bulan perak,…
Berhala serupa apa menetak kesumat?
Lidah logam berkarat
Sekarat,..
Sekerat tangis
Kapak Ibrahim di leherku
Kepala lelaki di kembang bambu
Langit sepi sekali
Sekali lagi ku asah badikku lewat darahmu
Ah betapa ingin segera ku kemasi namamu
Menjadi sepiring nasi
Dompetmu kosong?
Lihat! Langit di ujung matamu pucat pasi
Bulan perak jatuh di beranda rumahku
Kepalamu masih di tertancap di kembang bambu
Bulan perak puisiku
Pekalongan, 26/03/09
Yang Dalam Sembahyang
.jpg)
Dan langit yang kita tatap
Telah mencuri segala kenangan atas rindu
Kini ku sebut satu persatu sisa-sisa perpisahan
Yang serupa kabut jatuh
Yang merambat di kolong ranjangmu
Lautkah yang ombak dan berkecipak di lambungmu?
Dan telah ku ciumi bau rambutmu yang hutan
Yang gelap dan sesat atas segala jalan
Maka ilalang yang sembahyang
Adalah yang bergoyang dengan segala kutukan
Yang kau lupa mengaji ketetapan
Yang ku alpha menziarahi kepulangan
Semarang, 19/03/09
16 Maret 2009
Waktu Hujan

Senja berwana violet merayap juga di bibirMu lalu ayat-ayat yang terucap dan aku tak bosan memungut doa saat ku nemu jejakMu seperti percik darahku yang merayap di kaca
*Puisi ini masuk dalam antologi penyair 7 kota antologi puisi komunitas Hysteria Semarang berjudul "Mencari Rumah"
1 Maret 2009
Jejak-Jejak Pada Sebuah Kepulangan
 Malam di ujung matamu, itulah yang ku lihat juga merayap di muka jendela. Sesaat berharap ada yang diam-diam menyiumi punggung kita tiba-tiba. Tapi sepi memang tak pernah berhenti, dan mata air di kelopak ibu bermuara juga di jantungku. Kini, inilah kebiadaban yang dikutuki malaikat bertongkat sabit. Karena akhirnya malam melemparnya kembali ke sini. Saat kita benar-benar telah mengunci sepi ke dalam almari. Dan ia telah mencecap rasa asing dari darah yang lumer lewat garis-garis berlubang di leherku juga air matamu yang turut bercampur di sini. Serupa menu makan malam yang biasa di santap kunang-kunang di atas batu. Lalu dari perut mereka berpendarlah cahaya-cahaya lampu. Dan itu juga yang tertelan di kerongkongan dan urat-urat matanya. Keasingan yang telah kita ziarahi dalam kepurbaan yang bernama doa.
Malam di ujung matamu, itulah yang ku lihat juga merayap di muka jendela. Sesaat berharap ada yang diam-diam menyiumi punggung kita tiba-tiba. Tapi sepi memang tak pernah berhenti, dan mata air di kelopak ibu bermuara juga di jantungku. Kini, inilah kebiadaban yang dikutuki malaikat bertongkat sabit. Karena akhirnya malam melemparnya kembali ke sini. Saat kita benar-benar telah mengunci sepi ke dalam almari. Dan ia telah mencecap rasa asing dari darah yang lumer lewat garis-garis berlubang di leherku juga air matamu yang turut bercampur di sini. Serupa menu makan malam yang biasa di santap kunang-kunang di atas batu. Lalu dari perut mereka berpendarlah cahaya-cahaya lampu. Dan itu juga yang tertelan di kerongkongan dan urat-urat matanya. Keasingan yang telah kita ziarahi dalam kepurbaan yang bernama doa.“Apakah ia bisa berdoa?”
Ah! Sial!! Kenapa pula harus bertanya, sedang aku tak hendak memperdulikan itu. Karena inilah ketetapan. “Ah, malaikat ternyata juga punya nasib”.
Tuhan memang maha bijak. Sedang kau masih juga mengumpati namaku di garis tanganmu. Sedang dulu-dulu pernah ku katakan padamu, “aku bukanlah seorang pelayat yang baik”. Karena kegaiban yang benar-benar nisbi telah mengubahku menjadi seorang peragu, dan mulutku telah benar-benar terkunci untuk segala kebenaran. Maka kata-kata yang kau dengar hanya akan membuatmu bimbang. Tapi kau masih juga merindukanku. Dan malaikat itu telah cemburu.
Mengenalku, kau hanya akan memunguti kesialan.
Lalu seorang lelaki terduduk di atas batu. Tangannya menggenggam belati. Mulutnya menghisap candu, dan kepul yang menyeruak ke tubuh angin tercium bau mantra yang sekarat. Masih ada nganga yang menetes dan habis di tanah. Ia tak mampu menyarungkan kesumat. Kadang memang ada yang tak bisa terwakili lewat apapun. Dan sekarang, laki-laki itu tengah bersekutu dengan gaib, sembari menghitung-hitung nama yang harus di habisi malam ini juga.

“ini purnama ke tujuh” katanya. Bulan memang telah hilang.
Langit di sejengkal kepalanya hanya ingin mendekapnya dengan segala rindu dengan dikirimkannya hujan yang biru. Langit memang tahu apa yang harus terjadi. Termasuk dendam yang di tatapnya saat ini. Biarlah segala yang kasat mata menyeruknya menjadi batu seperti yang diduduki lelaki itu.
Aku memang tak ingin datang menemuinya. Karena ia hanya akan menemui luka-luka yang terselip di putik bunga kamboja yang ku bawa. Yang melenakanmu dan membuatmu berhenti waspada. Berhati-hatilah pada segala sesuatu yang diam tiba-tiba.
Langit di atas kita berwana jelaga. Mengeramkan sunyi juga kerindangan yang sama. Tapi seharusnya kau mengerti, di antara kita akulah yang paling terluka. Karena aku harus menimbang-nimbang segala kutukan. Dan aku ternyata adalah seorang peragu, termasuk untuk mengakhiri perjumpaan ini. Sampai ku putuskan juga aku harus menyudahinya sekarang. Membiarkanmu mengutukiku, sedang aku masih terus mengeja namamu. Entah dengan kegilaan apa. Tapi inilah akhir riwayat kita. Ada yang usai tiba-tiba. Dan aku sebenarnya tak mengerti apa itu, selain memang sebuah suara yang lindap dan runtuh di telinga kita berseru bahwa telah tamat amanatku. Aku yakin kau mengerti itu.
Maka simpanlah belati itu, setidaknya untuk saat ini. Karena aku takkan datang. Tapi tikamkanlah besok saat aku kembali mereka-reka. Tikamkan tepat di punggungku dan menembus keluar dadaku, saat aku tengah meramalkan hari matiku, dan segala kenaifan telah tanggal, bersama daun-daun yang jatuh ke tanah, juga darahku. Kuburkan aku tepat di situ.
Lihatlah punggungku, telah tumbuh sayap-sayap dari reranting kecil, yang tumbuh lewat benih kesunyian yang kau tancapkan tepat dan menyeruak di rusuk kiriku. Tapi aku mematahkannya, harus ku patahkan. Karena ku memang tak pernah memilih menjadi serupa malaikat, seperti yang kau kehendaki. Menggantikanmu memunguti arwah-arwah sakit yang tersangkut di riak-riak air, kulit-kulit pohon dan kediaman batu. Ah,.. itu terlalu menghabisiku. Karena kelak akupun harus memungutmu.
Maka biarkanlah segala sesuatu terjadi tanpa kita berencana dengan angan-angan yang basi. Aku pasti datang, tapi tidak sebagai kekasih yang kau rindukan. Karena aku hanya ingin menyapamu dengan sederhana saja. Mebawakanmu secangkir kopi dan kita kembali lesap dengan puisi-puisi yang terbata-bata bicara.
Aku telah memalingkan muka dari langit dan doa. Memilih berlari ke lembah-lembah berlumut dan goa-goa wingit. Ya, aku tak kuasa untuk menerima segala pemberian itu. Aku tak pantas!
 Dan lebih baik aku berlari sendiri. Memintal-mintal api juga puisi kerinduan padamu. Menangisi kepergianku sendiri darimu. Sendiri saja, sekalipun aku tahu kau pasti tahu itu. Maka kutuklah aku sekarang. Kutuklah aku menjadi apapun yang menjijikkan. Maka aku akan kembali bertandang. Seperti anak yang rindu rumahnya, rindu rahimnya.
Dan lebih baik aku berlari sendiri. Memintal-mintal api juga puisi kerinduan padamu. Menangisi kepergianku sendiri darimu. Sendiri saja, sekalipun aku tahu kau pasti tahu itu. Maka kutuklah aku sekarang. Kutuklah aku menjadi apapun yang menjijikkan. Maka aku akan kembali bertandang. Seperti anak yang rindu rumahnya, rindu rahimnya.Akh,.. seandainya saja aku dapat bermukim kembali di rahim ibu. Merebah di sana, ranjang dari sekat-sekat doa yang tulus. Rumah yang bijak dari segala kesunyian. Dan setan-setan tak kan berani melawat. Karena inilah kejujuran yang lebih jujur dari saat apapun. Dan tembangkanlah kidung itu sekali lagi di telinga kananku tepat saat kelahiranku.
Seseorang wanita tengah bercakap dengan kesendiriannya. Berpura-pura menjadi trotoar dan pejalan-pejalan lewat di atas tubuhnya. Tapi memang begitulah hidup. Orang datang dan pergi. Lewat dengan meludah dan berlari. Dengan cara apapun mereka telah tumbuh bersama bulu-bulu tubuh di punggungmu. Turut juga aku bersama kenangan yang galau. Aku menamainya perempuan bergaun jingga. Yah, selalu memakai gaun sewarna senja. Aku turut pula melawat kediamannya, tapi akh,..!! betapa rumah itu telah menghabisiku! Atau kedatanganku yang dianggapnya pencuri jendela-jendela, saat kebisuan tengah menyergap tepat saat kedatanganku? Hingga jendela-jendela itupun lari. Lari kedalam saku bajuku. Dan aku memang sengaja tak mengatakan pada rumah kediamannya juga kepada pemiliknya. Wanita bergaun jingga, juga rumah sunyinya, sungguh aku hanya ingin menyapa kalian dengan sederhana karena nama-namamu juga yang melayat di garis tanganku. Berdiam di atas trotoar dari punggungmu. Juga ranjang di kamar tidur rumahmu tak pernah lelah memanggil-manggil namaku.
Maka kekalkanlah ini. Kekalkan segala ayat yang kita eja bersama. Mari mengaji, dalam kebutaan yang gagu. Ketamakan yang pelan-pelan bersarang di dada kita. Aku menyakini itu. Karena kitalah kealphaan yang benar-benar tak mengerti.
Saat semuanya tanggal aku temukan juga catatanmu. Seperti kau biarkan saja saat anak-anak angin kita yang nakal menyerukkan segala kebisuan dari ingatanku. “Mungkinkah aku mengenalmu jauh sebelum kita memilih untuk berumah?”
Kepada tanah yang rebah dengan segala ramah. Aku ingin meminum nanah yang mengucur dari ibu jari kaki-kakimu, empat-empatnya. Inilah istirah dari kepenatan yang lelah. Inilah kealphaan baru serupa penyakit lupa yang menjangkitiku selalu. Maka aku hanya seorang pendengar puisi-puisi dari ranah keramat yang tajam. Serupa puting susumu, juga rerumput dari ranah kelahiranmu. Tajam menetak kebekuan yang berguling-guling lepas di lidahku. Walau tak semuanya ku simpan dengan baik. Karena harus ku rebus juga semua milikmu dalam ingatan batu.
Saat itu kau pasti menebak-nebak telah keluar dari betisku sebuah jalu. Berjalan dengan menancap-nancapkannya ke dinding kamarmu, juga di keningmu. Setelah semua usai segala garis adalah ayat-ayat yang begitu terang. Percik dari cigarette bapak yang melenting dibahu. Inilah ayat api! Dan kau telah mengutukku serupa pencuri. Maka ku amini juga. Karena aku memang pencuri. Akulah pencuri kecil yang dikasihi Tuhan,………………
………………………………. Akhhhhhh,….!!! Tuhan Baiatlah aku sebagai Pencuri!!!!!!!
Maka aku tertawa kecil saja. Juga saat kaupun mengendap-endap di daun telingaku. Mencungkili batu berwarna emas yang kau cintai. Uh,.. rupanya kalian juga pencuri. Ambilah sesukamu. Itulah hartaku yang takkan habis. Satu-satunya. Dan habiskanlah karena aku tak ingin mempunyai apa-apa lagi.
Atas nama puisi-puisi yang merambat di dadamu Inilah catatan terakhirku. (Barangkali, walau kau anggap pula lagi-lagi sebagai barang curian. hahahaha,….)
Inilah jawaban! Dari dari duka-duka saat mengaji namaku. Tapi aku takkan berebut, karena kau berkata pelayat berhak menziarahi mayat dengan tumbal apa saja. Sedang selalu ku persembahkan belati dan melati. TUSUKAN,…!!!! TUDUNGKAN,…..!!!!!!!
Sial!! Kau malah mengirimiku sepucuk rindu dari moyang ingatanmu. Rindu yang ku kuliti saat sendiri, hingga aku harus mengunci keranda-keranda basi dihalaman belakang. Menangis sendiri atas segala kepulangan. Dan puisi-puisi yang merambat di dadamu berkata “apa sudah saatnya?”
“Mari tidur disini” bisikku
“Sambil mengaji dan mengaji?” tanyamu
“Terserah!” inilah ranjang berkelambu ungu. Ada nama-nama. Kau hendak mencuri siapa?
Langit merebah dan mengirimkan kamboja di sela telingamu. Terimalah dengan sederhana saja seperti ia memberimu.
Malaikat itu datang lagi, dengan segala tangis yang ingin ku tangisi. Bulan sabit di pinggangnya ku curi, ku gantungkan di jendela tamu.
Ku kunci pintu. Kau kunci pintu.
Tanah melipat kita dengan sangat bijak,….

21 Februari 2009
Sepertinya Langit Memang Berjarak Selepas Januari Ini

Sepertinya langit memang berjarak selepas januari ini
Kita pun jatuh di punggung waktu
Bersama riwis yang tak sekedar gerimis
Daun-daun yang mengapung di jalan
Juga tulang-belulang leluhur
Menunggu di kubur
Sedang kita gelisah mencuri nama-nama di rak-rak buku
“Kau mencari siapa?”
Sepertinya langit memang berjarak selepas januari ini
Hujan pula yang mengendap di tapak-tapak kaki
“ini pertanda, langit mencintaimu” katamu
Sedang kita masih juga bertanya
Siapa yang harus lebih dulu berdusta,
Di balik matamu hujan tak juga reda
Sepertinya langit memang berjarak selepas januari ini
Lewat logam-logam yang jatuh di gang-gang sepi
Juga sajak-sajak yang tanggal disebalik punggung kita yang saling lekat
Saat kita masih juga bertanya
Siapa harus menghabisi
Siapa
Semarang, 12/02/09
18 Februari 2009
Bulan di Rumah Sunyi

; Kekal Hamdani
Tangan kananku basah
Tapi hujan tak sepenuhnya bersalah
Bulan,... Bulan,...
Aku singgah di kerut-kerut mukamu
Dan gemeretak pada laut yang ibu
"dulu aku mencuci muka di sini"
Mencuri-curi lebam yang ku sisipkan di saku bajumu
Terimalah tenungku dari muara rindu
juga kutuk yang merayapi warna rambutmu
Pudarlah,... Pudarlah,...
Api-api dari doa yang sunyi
Jatuh atas nama rumah
Ku cium tanah
Kekal di sisi batu
Sisa Perjalanan di Beranda Rumahmu

Betapa nama-nama di garis tanganku
Telah terhenti pada sudut rumahmu
Dan hujan lagi-lagi mengaduh
Tentang gemeretak yang usai saat subuh
Ah,.. aku pulang
Sisa perjalanan hanya istirah
Di kursi beranda dari punggungmu
Yang kau sisakan jauh sebelum luka-luka menepisku
di depan pintu
Aku mengeram sunyi di sini
Memintal api
Dan kita menari
Sampai sesaat sebelum pagi
Anak-anak kita kan bertanya
“abu siapa berserakan dan mengotori halaman depan?”
14 februari 2009
8 Februari 2009
Dan Sabit. Pulanglah,..

Sedang sabit yang menetap di keningmu
Selalu menetak jalan-jalan di leherku
Maka lewat hujanlah aku istirah
Dan kau tak pernah sudi menyerah
Tetirah kepada padang-padang dan beranda-beranda rumah.
Pulanglah, ku tembangkan sajak-sajak tanah
Seperti saat kelahiranmu,
Ku tembangkan mijil di telinga kananmu
Pertanda kijingku di keningmu
18/01/09
Bulan tak Utuh

Bulan memang tak pernah utuh seperti katamu
Ruas-ruas bambu di bawahnya merapalkan mantra-mantra
Seorang lelaki bermain simpul-simpul luka
Ah,.. hantu-hantu menyeruak di kelopak mataku
Serupa debu
Sejak itu aku selalu menangisi kepergianmu
Maka ku kunci bulan perak dan berhala batu
Dendammu ku sarungkan
Angin selalu patah sejak itu
Semarang, 07/02/09
2 Februari 2009
Perbincangan Melalui Puisi. Perbincangan yang Menjadikan Kita Sebagai Sebuah Puisi

Malam kemarin, aku sedang merasa kebingungan yang tiba-tiba. Aku ingin menulis puisi tapi hanya sebait saja yang mampu ku tuliskan. Puisi itu berbunyi; "Dari batu yang selalu kekal saat matiku,/Seorang duduk di atasnya sembari bersekutu mengutuki gaib,/Yang sial mencuri waktu di desing telingamu,/“Rahasia,… kita diam-diam saja bercumbu//”. Aku berfikir,.. mungkin saling berbagi puisi mengasikkan. Maka sebait puisiku tadi ku kirimkan ke beberapa orang teman antara lain; Gema Yudha, Anthoni, Wikha Setyawan, eL dangauilalang, Neto, juga mas Agung Hima dan Khumaida. Dan apa yang terjadi? Aku mendapat kiriman balesan puisi yang banyak dari mereka dan dalam waktu yang hampir bersamaan. Maka ku tulis lagi puisi-puisi buat mereka, dan tentu saja berbeda untuk masing-masing. Setelah berakhir aku mulai terbata-bata. "aku menulis puisi?". Ku baca lagi puisi-puisi dari mereka dan puisi-puisiku yang ku kirimkan kepada mereka. Ah, aku tersadar ,.. Aku merasa ada perasaan yang sama antara kami. Aku hendak bermain dengan kata-kata yang telah lahir ini. Kesadaranku bahwa kami saat ini senada dan puisi-puisi kami adalah serupa. Bahkan kami mungkin bagian kecil dari puisi itu. Berloncatan, dalam kegamangan. Maka kurangkai lagi puisi-puisiku yang kutulis barusan dan puisi mereka. Menjadi satu puisi yang utuh. Sebuah percakapan dengan puisi. Seolah menjadikan kami satu puisi.
Aku sadar puisi dapat lahir dengan berbagai cara. Tak perlu satu penyair yang sedang terbata. Bahkan mungkin puisi dapat lahir dari perbincangan yang senada. Antara kau dan aku.
Dan lahirlah puisi untuh ini dan ku beri judul;
Dari Kegaiban Yang Menjelma Kata di Dada Kita
Dari batu yang selalu kekal saat matiku
Seorang duduk di atasnya sembari bersekutu mengutuki gaib
Yang sial mencuri waktu di desing telingamu
“Rahasia,… kita diam-diam saja bercumbu”
Kemudian kata-kata lindap di udara yang senyap
Seorang lelaki menanam tawa di pucuk batu
Jembatan kayu memanggilnya pada tubuh yang layu;
“kemari, kemari, titipkan lukamu padaku”. (Gema Yudha)
“Jembatan itukah aksara-aksara dari tubuhmu?”
Aku datang, datang menujumu
Dan telah ku bawakan oleh-oleh kepala bocah
Tumbal yang mengeja riwayatmu
Sial kau! Nama-nama di celah jendela mengumpati ragu di matamu
Ah betapa gila! Orang-orang di depanku serupa berhala
Bergoyang-goyang, meraba, dan tertawa
Sabit di pinggangnya masih ada bekas darahmu
Menari di atas kepalaku
Gelas-gelas di belakangmu
Berisi gelap yang ganjil
Serupa bohlam yang menunjukkan arah kencingmu
Tapi kau pilih abai di puncak batu. (Antoni)
Bahkan langit di sejengkal kepala kita
Takkan tahu siapa mengeja namaku
Aku tak memilih apapun
Sadang gayung yang ku siramkan,
Mengalir juga di saku bajumu
Kau titipkan lukamu di daun-daun layu
Mencoba menggapai abai pada jerit tawa orang-orang di depan kita
Mungkin kaulah batu yang diam-diam menanam kelam
Lalu tubuhmu mendaraskan kata-kata yang,
Berharap,
Menikam malam diam-diam. (Gema Yudha)
Di sebelahku patung lembu
Ku buat dari doa dan ia menertawaiku
Sedang malam-malam serupa wajahmu
Bawakan aku reranting cahaya
Yang kau tangkap di udara
Orang-orang kini gagap ditelan senyap
Ku benamkan kata-kata di wajahku
Ejalah serupa doa yang di rajah orang tua kita
Kata-kata akan sampai
Tapi selalu mungkin untuk tercerai. (Gema Yudha)
Di sanalah asalnya luka,
Semacam pisau lipat yang selalu berdiam di rusuk kirimu
Menikam ke dalam (eL Dangauilalang)
Bahkan aku selalu menerima luka-luka yang matang di sepunggung bonekamu
Kekalkan ini, dan kita tertawakan nganga
Ia tak bisa berbuat apa-apa
Bahkan untuk menusuk rusuk kananku
Berlubang dalam kenanganmu
Menjelma jantra,
untuk tangan yang tekun
menenun air mata (eL Dangauilalang)
Masihkah kau mengeja tiap-tiap huruf
Dalam mushaf-mushaf pada kitab-kitab?
Ataukah kini kita sedang terjebak
Dalam semesta pekat tanpa ujung.
Percumbuan itu sudah terasa anyir
Saat kau bawakan secangkir kopi pagi tadi. (Neto)
Sedang selalu saja ada kemungkinan
Yang menceracau pada keutuhan dalam diam
Aku mengekalkan sebuah angin
Yang menghabisi puntung rokokmu
Saat kau terbata, bagaimana cara menelan puisiku
Bagaimana mungkin ku telan puisi-puisi
Yang kau sajikan rapi dengan appetizer dan delight sundae itu
Sementara kau terus kucurkan nipis
Pada semua luka yang kau goreskan
“Setebal itukah kau bangun puing dalam gedung pencakar langit yang terpadatkan kata? (Neto)
Maka kau cukup melihat saja
Kata-kata yang hendak ku bangun di atas nisanmu
Aku hanya ingin menulis riwayat di garis tanganku
Maka berpendarlah kau
Sembari kupasi tiap helai merpati yang ku kirimkan kepadamu. (Neto)
Ku trima itu
Aku ingin menciummu
Sebagai istirah yang tenang atas percakapan kita yang bisu
Sst,.. Maka sunyikanlah bisikmu
Bersama ramainya tetes hujan pada bulan desember. (Neto)
Ku temukan hujan di kelopak matamu
Terlempar
Mereka-reka
Kemarauku
Yang beludru
- Suatu malam - (Wikha Setyawan)
Ah kau mengingkari waktu!
Kau mengingkari waktu!
Sedang puisi-puisi yang merambat di dadamu selalu saja bertanya
“Apa sudah saatnya?”
Yah aku meyakini puisi adalah dunia yang mampu menarik siapa saja pasa sebuah ruang. ada bahasa yang ku baca, ada spiritual yang ku eja. maka siapa saja yang yang telah menjejak di bahuku. mari kita melebur bersama. tak hanya dalam kata tapi pada titik yang sama. ruang yang membuat kita sama-sama berkaca. I Love U
24 Januari 2009
Andai Saja Kau Tahu
Sebelum jejak-jejak angin habis
Sajak-sajakku telah kikis bersama secangkir kopi manis
Yang telah kuhidangkan di meja tamu
Jauh sebelum subuh menepismu
Di depan pintu,
Aku hanya mampu memandangmu lewat celah jendela
Menanti kau masuki ruang-ruang luka
Dari sini telah ku sisakan nama-nama
Yang kubaca dari garis-garis patah di tanganmu
Setiap satu bait kita lahirkan dosa
Semoga saja kau tahu,
Aku hanya ingin membuat Tuhan tertawa
Semarang, 16/01/09
21 Januari 2009
Gerbong Kereta

Gerbong-gerbong kereta ialah isyarat keranda
dan nisan hanyalah jurusan
hendak ke mana kita berpulang
saat loket di buka
orang-orang bergiliran mengantri pada penjagalan
Denting lonceng,
pilar-pilar tegak ialah isyarat
pelayat menunduk dan mendoa
saat gerbong-gerbong kereta semakin jauh
ke arah rembang
pada stasiun tak bernama
di kota tua yang terlupa
masih ada perbincangan terakhir
hingga aku mengingatkanmu
akan roda sejarah terakhir yang datang
yang tak bisa menanti
dan suara peluit kereta ialah sasmitha
mengingatkan untuk berjejalan
bersama wajah-wajah pucat
mengantarkan pada kota
yang lama kita tanggalkan wajahnya
dari ingatan
– “Aku harus berangkat” katamu –
kelak bila jumpa,
hendakkah kita bisa saling menyapa?
dan aku lebih memilih rebah ke rumah malam
dari pada menungguimu diusung gerbong keranda
pada akhir sebuah peradaban
Gerbong-gerbong kereta ialah isyarat keranda
dan nisan hanyalah jurusan
hendak ke mana kita berpulang
maka seperti pelayat
ku titipkan doa lewat kamboja
saat denting lonceng semakin riuh
dan rembang semakin berlabuh
Semarang, 5 Februari 2007
19 Januari 2009
Di Atas Sajadah Batu

kita tak henti melenakan rindu
betapa keras kepala beradu
dan tanah betapa rela menerima darah
seperti sungai mengendapkan prahu
mengalirkan bunga-bunga salju
juga sayap-sayap ibu
ke muara itu
angkuh
dan biru
di atas sajadah batu
kita terus mentasbihkan bisu
yang kekal merayap di daun
di lembayung kering
juga telinga kita enggan menerima bising
Kau menantiku dalam wening
aku mentahlilkan nama abu-abu
Semarang, Maret 2008
puisi ini masuk dalam antologi bersama "Aku Ingin Mengirim Hujan"
15 Januari 2009
Di Dalam Kamar Kita Bertaruh

Kita telah bertaruh di atas batu
Tentang kabar yang layu atau matang di dada perawan
Sedang telah ku sulut lilin-lilin di atas bahumu
Sebagai penanda malam yang istirah di rimbunan rambut
Sebelum aku mengeja kelopakmu diam-diam
Orang-orang tak berlidah mengejek di luar pintu
Dan kita masih merengek di atas batu
Hujan tak juga datang
Semarang, 14 Januari 2009
12 Januari 2009
Catatan Ngawur dari mas Agung Hima

AKU INGIN KESANA, mengendapkan laraku. Jan 3, '09 11:09 AM
for everyone
Category: Other
AKU INGIN KESANA, mengendapkan laraku.
[catatan ngawur untuk puisi-puisi Pandu]
[1]
Biasanya anak-anak muda yang pernah jatuh cinta, sedikit banyak pernah menulis apa saja yang dirasakannya dimana saja dan dalam bentuk apa saja. Salah satunya adalah puisi. Biasanya pula, puisi yang ditulis mendayu-dayu, lembut dan passion banget. Puisi jenis seperti ini bisa meloncat-loncat liar, tak terdeteksi oleh estetika bahkan kadang lebih bicara tentang remeh temeh, berkaitan dengan yang dirasakannya. Tapi bagaimana jika sebuah puisi yang ditulis ketika anak muda itu telah melewati hal-hal seperti itu, dan menemukan dunia baru yang sama sekali tidak dimengerti oleh orang lain dan mungkin juga dirinya sendiri?
Apa yang mungkin dipilih dalam pengolahan kata-kata yang dikumpulkan dalam sajak yang diciptakannya? Apa yang ingin disampaikannya ketika puisi itu sudah menjelma utuh di depan pembacanya?
Pandu, saya kenal belum begitu lama, yang saya tahu dia mahasiswa sastra dan bergabung dengan kelompok teater semarang. Perkenalan kami sangat aneh, pernah bertengkar dan tiba-tiba saja begitu akrab, dan tahu-tahu menunjukkan puisi-puisinya. Saat itu ia menunjukan puisinya yang ditulisnya semasa SMA, sejak itulah saya mengerti ia sarat dengan kontemplasi. Saya tidak menduga ketika membaca puisi SMA itu ditulis dengan penuh perasaan dan sangat berbeda dengan puisi anak-anak SMA lainnya. Saya melihat ia begitu dewasa dan seperti sudah begitu dekat dengan cinta itu sendiri.
Dan suatu hari ia menunjukan puisi-puisi terkininya, sarat metaforis yang manis. Metafora yang dia keluarkan langsung mengikat kuat dalam pilihan katanya. Meski untuk beberapa hal ia masih kebingungan dalam menggunakan metafora tersebut, tapi saya yakin bahwa itu adalah berdasarkan pengalaman empiris yang dia alami dan akan semakin matang. Tengoklah sajak lelaki dan hujan saat desember.
Seorang lelaki mengenakan tubuhku lewat desember yang basah
Berbiak di depan pintu dan mengguruiku
Tentang batu-batu berwarna merah
Aku serupa arwah dalam kabut gaib
Berwajah sakit
Seperti kita ketahui bahwa kata atau bentuk bahasa mempunyai relasi dengan dunia nyata. Sehingga istilah referensi digunakan untuk merelasikan bahasa dengan yang bukan bahasa, di lain hal ada relasi unsur bahasa dengan pengalaman seseorang. Relasi inilah yang disebut pengertian (sense) (1). Maka di dalam puisi Pandu berlalu lintas relasi antara bahasa dengan dunia pengalaman dan relasi antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Seorang lelaki mengenakkan tubuhku, mempunyai makna yang sulit dipahami. Pada kalimat tersebut ia seperti bercerita tentang persoalan psikologis yang kuat. Ada semacam persetubuhan penting didalam pengalaman hidupnya lewat desember yang basah.
Saya kemudian menangkap ada sebuah harmonisasi yang disepakati sebagai kata yang bisa mengungkapkan gagasan atau merangsang ide. Jika disadari bahwa kata adalah penyalur gagasan tersebut maka kalimat awal dalam puisi itu membuka ruang baru untuk menstimulus siapa saja pembacanya ke arah imajinasi lain. Kalimat selanjutnya, berbiak di depan pintu dan mengguruiku, tentang batubatu berwarna merah, adalah sebuah kematangan dalam pemilihan kata/diksi (2). Maka suatu kekhilafan jika dalam puisi beranggapan bahwa pilihan kata adalah persoalan sederhana.
Saya masih percaya bahwa persoalan ini bukanlah persoalan yang bisa terjadi dengan sendirinya atau tidak perlu dipelajari. Sebab sebagaimana keseharian, banyak kita jumpai orang-orang yang kesulitan mengungkapkan maksudnya dan miskin variasi bahasanya, juga kita jumpai orang yang boros dan mewah mengobralkan perbendaharaan katanya namun tidak ada isi yang tersirat di balik kata-kata itu. Maka ketika puisi menjadi sebuah hegemoni untuk mengungkapkan kasunyatan dalam bahasa alegoris, semua itu sangat diperlukan.
Aku serupa arwah dalam kabut gaib, berwajah sakit. Sebenarnya sampai kalimat ini, saya sudah merasakan kecukupan. Ibarat disuguhi Le paillard yang lezat tiba-tiba saya harus menghabiskan beef stroganoff, sirloin, tambah Roast beef platter dan semua harus kutelan dalam hitungan itu juga. Maka secara pribadi saya kembali membuka ruang baru dengan siapa saya berhadapan kali ini.
[2]
Asu! Kok aku dadi serius ya? Puisine Pandu kok diseriusi! Mumet malah! Membaca puisi Pandu, saya seperti diajak rekreasi dalam dunianya yang lain. Dunia yang jarang dijumpai oleh anak-anak muda jaman sekarang. Saya mendapati seorang anak muda yang begitu tekun melakukan kontemplasi. Saya tidak akan menghakimi apakah dia melakukannya dengan benar atau tidak, namun ia bersikukuh dengan apa yang tengah dijalani saat ini. Barangkali ia sudah menemukan kebenaran yang memang didambanya setiap saat, bahkan saat ia mengalami sebuah perjumpaan ataupun perpisahan dengan sesuatu yang dicintainya.
Di dalam puisi-puisi Pandu saya tidak mendapati setiap katanya diawali dengan biasa saja, kata yang dipilihnya adalah pembentukan karakter hidup dia sendiri. Saya tidak menemukan kata-kata yang sia-sia. Barangkali kelemahannya adalah ia belum mendapati sebuah acuan yang pas antara bentuk dan referen (3) sehingga menimbulkan makna atau referensi yang timbul akibat hubungan bentuk itu dengan pengalaman non linguistik atau barang-barang yang ada di alam. Semisal ada kalimat nares, maka tak banyak yang tahu. Ia harus diberi petunjuk dengan sejumlah referen hidung, telinga, matahari atau gunung. Untuk membantu mengetahui makna itu maka ditunjukanlah barang yang sesuai dengan itu, yaitu hidung.
Lha, saya sendiri tidak tahu, apakah Pandu juga mengerti tentang hal ini, seharusnya sebagai mahasiswa sastra tentu yo ngerti banget. Atau jangan-jangan ia jarang berangkat kuliah? Nah lo! Saya pikir ini adalah jebakan ketika membuat puisi, meski saya percaya bahwa puisi akan lebih dinikmati ketika keluar dari rasa-nya, namun akan lebih baik jika mengalami keseimbangan dalam hal apapun. Sehingga ketika disuguhkan ke pembaca, serupa kesempurnaan esetetika itu sendiri, puisi adalah sebuah spiritual achievement yang layak konsumsi.
Tak saya pungkiri bahwa puisi Pandu mempunyai daya stimulus untuk memulai sebuah perenungan. Lewat pengkayaan kata yang dimilikinya, ia menawarkan sebuah rekreasi pengalamannya. Dalam puisi SAAT MENGAJI kita akan dibawa pada sebuah pengalaman spiritual yang aneh. Barangkali pada hijaiyah awal, ia sudah menemukan apa yang diimpikannya saat masih kanak-kanak. Sebagaimana judul yang dipilihnya saat mengaji sangat berbunyi proses ia melakukan iqra. pembacaan yang dialaminya inilah yang kemudian membuka curhat-nya lewat puisi ini.
Maka pada sub judul ayat-ayat api, saya menemukan dirinya pada sebuah ruang dimana ia merasa menjadi kaf fa’ ro’. Bagi saya, adalah sebuah keberanian menyebut dirinya sendiri kafir! Inilah sebuah proses awal bagaimana memahami iqra itu secara konsisten. Sebagaimana keinginan purba manusia yang selalu mencari kebenaran, maka Pandu dalam puisi ini bercerita menemukan kebimbangan yang dijalaninya, seorang lelaki melemparkanku ke dalam kitab abu-abu, bahkan padanya aku tak tahu hendak kemana puisi ini menuju.
Lha saya sendiri hanya tersenyum saja, apapun proses seperti itu memang layak dijalaninya. Dalam hati saya bertanya, kenalin dong lelaki yang melemparkanmu itu.hehehehehehe.
[3]
Puisi Pandu memang tidak akan segera mudah dipahami, selain mempunyai kekuatan semantik seperti yang saya sebut diatas, ia kadang juga terjebak dalam flooding yang dia ciptakan sendiri. Ada semacam ketidakpercayaan pada dirinya untuk menghentikan kata. Sehingga pada beberapa puisi, maksud yang harusnya sudah tersampaikan menjadi bias kembali. Pembaca akan berputar-putar pada sebuah estetika lain lagi. Maka jika puisi menjadi alat ungkap, maka Pandu tidak bercerita secara normal.
Namun saya yakin, bahwa dengan waktu ia akan bisa lebih jeli untuk kembali memilih kata yang akan ia ungkapkan. Yang patut disadari adalah bahwa makna kata tidaklah statis, perubahan inilah yang akan dihadapkan kepada kita tentang kesulitan-kesulitan baru bagi pemakai kata. Sebab itu untuk menjaga pemilihan kata, sebaiknya setiap penutur bahasa memperhatikan perubahan-perubahan makna yang terjadi.
Bagi saya pribadi, puisi Pandu ingin bercerita banyak hal konteplatif, meski dibalut dengan relasi-relasi yang kadang menyebal dari itu. maka saya selalu bisa menikmati puisinya. Sambil nggaya sok tahu bisa menangkap apa yang diceritakannya, maka aku ingin kesana, mengendapkan laraku. Bukankah semua orang mengira tidak mempunyai lara, padahal rumahmu tidak mencuri apapun darimu. Tapi harus kemana aku mengendapkan laraku? Wasyah! [agunghima]
1. Dalam pengertian sehari-hari disebut juga makna, entah makna kalimat, makna structural dan sebagainya. Bidang inilah yang disebut dengan semantic structural yang seringkali dipertentangkan dengan semantic leksikal.
2.Dalam pengertian ini jauh lebih luas daripada apa yang dipantulkan kata-kata saja, tidak melulu kata yang mengungkapkan suatu gagasan atau ide. Meliputi juga fraseologi yang mencangkup kata dan pengelompokannya, gaya bahasa sebagai bagian diksi yang bertalian dengan ungkapan individual atau karakteristik bernilai artistic tinggi.
3.(barang yang diwakilinya) Menurut odgen dan Richard dalam the meaning of meaning, symbol adalah unsure linguistic (kata atau kalimat), referen adalah obyek (dalam dunia pengalaman), sedangkan referensi atau oikiran adalah konsep. Menurut teori itu tak ada hubungan langsung antara symbol dan referen, hubungannya harus melalui konsep.
Gp, 2 jan 09; 03.50”
Tulisan ulasan ini dapat di lihat di; http://agunghima.multiply.com/
Ditulis untuk diskusi kecil pembacaan karya puisi Pandu. Retro Studio, 2 jan 09
Buat Mas Agung Hima, matur suwun ulasannya.
10 Januari 2009
Kereta di Mata Ibu
saat gerimis perlahan
penanggalan almanak tertahan
dan jejak-jejak sejenak
terhenti di stasiun
kereta tak jalan
tertahan
di sudut matamu
Puisi ini masuk dalam antologi Puisi bersama "Aku Ingin Mengirim Hujan"
5 Januari 2009
Orang-Orang Bermata Batu

Selayaknya lewat jemariMu aku tulis semacam puisi
Sajak tentang luka karena dada kita yang renta
Aku tak hendak berkata bahwa aku sang penebar hujan
Tapi lihatlah gerhana di korneaku
Sedang orang-orang bermata batu tengah berbisik-bisik curiga
Lalu mereka kirimkan luka-luka baru di alas sujudku
Sementara dalam tafakurku lihatlah aku tak menangis bukan?





 RSS Feed (xml)
RSS Feed (xml)