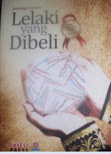Kau sudah mulai kelelahan sepertinya. Mencatat setiap kealphaan, mendengar setiap keraguan. Sampai harus kau tutup pintu mati-matian. Menyuruhku pergi sebelum aku sempat mendekapmu. Sedang sejak kita bertemu pernah ku katakan padamu, mengenalku kau hanya akan menemui kemalangan.
Kau sendiri yang memaksaku sebelum kau tak mampu melepasku. Aku pergi karena memang kau harus sendiri. Memintal doa-doa di sudut sepi. Air matamu yang deras bermuara di muka pintu. Memanggilku untuk kembali.
Sudahlah, pintumu memang telah patah di tubuh angin yang sama sekali tidak pernah kita panggil, dan kau terus menambalnya dengan air mata. Bersyukurlah kita masih bisa menangis.
Rindu memang memilih ujungnya sendiri. Pintu itu juga telah memilih tamunya sendiri. Kau tinggal duduk dan memulai percakapan. Aku tak peduli jika sesabit bulan yang lama kau eram telah memutus pergelangan tanganku saat ku genggam tanganmu.
Pintu itu pula yang melempar kita pada ranah yang sama. Di kota penuh kutuk. Kita juga di kutuk. Menjadi angin yang tak tahu sarangnya. Hanya berpusing di tanah tandus dan mengirimkan debu di mata para musafir. Mencium punggung daun, menarik-narik tangkainya, lalu putus.
Setidaknya kita tidak jadi badai yang mengangkat atap dan doa-doa ke langit itu, yang ketika sampai di sana segalanya hanya akan terbakar. Karena beribu-ribu malaikat penjaga takkan sudi pelataran rumahNya di masuki begitu saja, kecuali tamu yang memang telah di tunggu.
Dan itu bukan kita.
Aku ingin tertawa sekarang. Aku juga melihatmu tersenyum lepas. Kenapa dulu aku tak memaksa untuk tinggal. Menanggalkan segala kecurigaan. Membiarkan sabit itu memotong-motong tubuhku yang lain. Sedang aku tahu telapak tanganku masih kau genggam. dan kita bertemu kembali untuk menghitung sisa-sisa percakapan.
"aku mencuri tanganmu" katamu.
"aku mematahkan daun pintumu"
"Sialan!"
Memang! Sekarang aku hanya berharap dapat mencium bahumu diam-diam, dan saat kau palingkan tubuhmu aku telah menghilang. Bersama angin yang menunggu di depan pagar. Menjadi kedukaan yang kau tenun rapi dalam ingatan.
Aku tahu tak ada orang lain yang kau biarkan masuk, walau banyak yang mengetuk. Selain aku, dulu. Terima kasih sayang.
Sekalah air matamu dan tahanlah tangismu. Pintu itu akan membuka dan memilih tamunya sendiri. Kau tinggal duduk dan mengulang percakapan.
Semarang, 14/09/09





 RSS Feed (xml)
RSS Feed (xml)