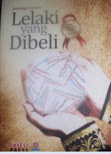Bahkan saat daun-daun kamboja itu tanggal karena angin serupa golok yang mengibaskan tubuhnya tak tentu arah, juga beberapa kembang kamboja putih jatuh di bahu Prayoga, seperti hendak memutus tatapan lelaki itu yang terus menajam. Tapi tubuh kekar itu telanjur kaku dan ia benar-benar tak tahu.
Pohon-pohon bambu berderit seperti jerit yang tak lelah menjaga isi pemakaman, yang menyadarkan peziarah, inilah dunia asing dari dunia luar yang bising tak karuan, yang hanya ada sepi dan kesedihan telah dikubur dalam-dalam. Tapi Prayoga masih saja tak bergeming dari tempatnya berdiri mencuri perhelatan ganjil ini.
Yah, barangkali dia memang tak perduli. Saat ini dia hanya berfikir dan benar-benar ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di depan matanya.
Orang-orang gila itu, kenapa mereka menangis?
Orang gila memang suka menangis tiba-tiba, tertawa tiba-tiba. Tapi ini? Orang-orang gila sekota menangis meraung-raung di kuburan Kaji Marjuki sejak pertama sampai sekarang genap seminggu beliau dimakamkan?
“Dasar gila!”
“Ini apa?” Batinnya.
********
Aku masih tak mengerti apa sebenarnya yang ada dalam benak bapak. Apa yang selalu bapak kerjakan, bahkan sejak dulu memang selalu membuatku tak pernah paham, seperti beberapa tahun lalu, saat dia menghibahkan beberapa hektar sawahnya kepada para bahu yang telah mengabdi kepadanya sejak puluhan tahun tanpa memungut uang ganti sepeserpun dan hanya menyisakan sawah seluas beberapa meter untuk digarap sendiri, lalu sekarang sebuah berita mengejutkan tentang bapak dari mulut Lek Muksin benar-benar membuatku gamang.
Kini ia bahkan telah berbuat jauh lebih gila dan apa yang kudengar ini masih tak bisa sepenuhnya kupercaya. Kebanggaanku kepada bapak atas gelar mulia bernama Haji itu segera saja memudar, berubah menjadi semacam keheranan yang sangat.
“Apa Lek? Setiap hari bapak pergi keliling kota hanya untuk mencari orang gila dan diciumi tangan-tangan najis itu?”
“Iya mas. Mulanya saya sendiri tak percaya dengan apa yang saya lihat tapi memang itulah adanya. Mbah Kaji beberapa bulan setelah mengikuti pengajian tarekat menjadi sangat aneh. Setiap pagi-pagi sekali sehabis sholat subuh berjamaah dia pergi entah ke mana. Karena penasaran ya akhirnya saya ikuti. Dan setelah berlelah-lelah berjalan menempuh jarak kiloan meter mengikutinya jauh di belakang akhirnya saya tahu dengan mata kepala sendiri dia pergi ke sudut-sudut kumuh kota ini hanya untuk mencari orang gila. Setiap ketemu Mbah Kaji langsung menciumi tangan dan wajahnya dengan menangis sesenggukan dan memeluk erat tubuh-tubuh terkutuk itu”. Jawab Lek Muksin dengan sangat yakin
“Tidak hanya itu mas. Hampir satu bulan ini keanehanpun mulai menghinggapi kampung. Orang-orang gila itu satu-persatu datang dan pergi ke rumah Mbah Kaji setiap hari. Mereka hidup dan berkumpul jadi satu dengan Mbah Kaji Marjuki”. Tambah Lek Muksin
Semua berita itu serasa benar hampir memecahkan gendang telinga dan jantungku. Aku tak bisa percaya begitu saja. Tidak mungkin seorang Haji yang harusnya berada dalam keadaan mulia dan suci tiba-tiba memilih hidup bersama kotoran dan kenajisan di sekitarnya. Tapi setidaknya itulah yang diceritakan Lek Muksin, tetangga sebelah rumah sekaligus bahu bapak yang paling setia mengabdi dan menggarap sawah bapak sejak puluhan tahun lalu.
Bahkan menurutnya kedatangan orang-orang gila setiap hari ke rumah bapak mulai meresahkan warga kampung. Kampung kelahiranku itu seakan diteror oleh sepasukan orang-orang tidak waras yang menebar bau busuk dengan tingkah-tingkah aneh yang kadang dianggap banyolan oleh anak-anak kecil, tapi bagi orang-orang dewasa dan tidak gila sepertiku tingkah-tingkah orang gila adalah ancaman bagi kami orang yang masih waras. Mereka hanya membuat onar dan kampung kami terlihat menjadi semakin kumuh, najis dan nggilani. Gila adalah penyakit menular yang akan menjangkiti siapapun didekatnya. Itulah kenapa orang kampung merasa benar-benar terancam dengan kedatangan mereka.
Pak Lurah dan para tetua kampung sudah datang ke rumah untuk menanyakan dan menghentikan tingkah bapak itu, tapi bapak justru menyangkal bahwa orang-orang gila itu memang datang sendiri ke rumahnya dan tak ada yang bisa bapak lakukan selain menerima mereka seperti tamu-tamu lainnya.
“Bukan saya yang menghendaki orang-orang gila itu untuk datang. Mereka datang sendiri dan sayapun juga tak mengerti kenapa saban hari selalu saja ada orang gila yang datang. Bukankah mereka mempunyai jalan pikiran sendiri yang entah apa itu dan tak pernah bisa kita mengerti?”
“Kalo ingin tahu kenapa mereka datang ke rumah saya, ya silahkan saja bapak-bapak tanyakan sendiri ke orangnya. Mereka datang ke rumah tanpa mengetuk pintu. Sudah ada di emperan atau di dalam rumah dengan tertawa-tawa atau menangis. Saya juga tak bisa apa-apa selain membiarkan saja mereka. Kadang kalau ada makanan saya berikan. Saya tidak bisa makan sendirian sedang ada banyak tamu yang bertandang dan duduk di rumah saya.”
Jawaban bapak semacam itu membuat lurah dan para tetua kampung tak bisa bicara apa-apa termasuk Lek Muksin yang juga sudah membujuk bapak berkali-kali. Dan kali ini Lek Muksin datang ke rumahku untuk menceritakan apa yang telah terjadi dengan bapak sekaligus juga memintaku membujuk bapak agar mengusir orang-orang gila yang selalu datang dan pergi tak henti-henti. Mungkin karena aku adalah anak tertua sekaligus yang paling dekat dengan rumah bapak karena adik-adik semua sudah menetap di luar kota dan hanya aku yang tinggal sekota dengan bapak.
Maka pada hari itu juga ditemani Lek Muksin aku pulang ke rumah kampung. Mencoba mencari kebenaran atas apa yang telah terjadi dengan bapak. Berharap apa yang dikatakan Lek Muksin hanyalah dagelan atau akal-akalan bapak supaya aku menjenguknya. Mungkin beliau sedang kangen sama anak-anaknya dan minta sama Lek Muksin yang bahu setia bapak itu untuk mencari cara supaya aku mau pulang. Aku memang telah hampir setengah tahun ini tak menjenguk bapak sejak kepulangan bapak naik haji. Rencanaku pulang mudik sekalian lebaran yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi kedatangan Lek Muksin yang tiba-tiba juga rentetan cerita tentang bapak kali ini benar-benar telah berhasil memaksaku untuk harus pulang kampung.
Tapi setelah perjalanan hampir satu setengah jam dan akhirnya bersama Lek Muksin sampai juga di rumah, tak ada kata-kata lagi yang bisa bisa keluar dari mulutku mendapati apa yang tengah berlaku. Aku benar-benar ingin menyangkalnya tapi apapun itu, inilah kebenaranyang terjadi, yang menyusun tubuhnya sendiri didepan mataku.
Bapak tengah makan dan menyuapi barisan orang-orang gila yang duduk di bawah meja makan?
Dagelan macam apa lagi ini? bapak sedang makan siang satu piring dengan orang-orang gila bahkan menyuapi mereka dengan tangannya sendiri?
Melihat kedatanganku bapak tampak begitu terkejut. Orang-orang gila yang tengah terduduk itu melihatku lalu tertawa terbahak-bahak. Sebagian ada yang menangis dan meronta-ronta minta suap. Ada semacam rasa takut dan keresahan yang menyergap saat menatap mata mereka yang kosong dan mulut mereka yang menganga, tampak gigi mereka kuning gading, tubuhnya belepotan sampah dan tercium jelas bau busuk menyebar penuh di dalam rumah dan hidungku, memancing rasa mual yang meledak-ledak di perutku.
Dengan setengah berlari bapak menghampiriku, dipeluknya tubuhku yang setengah kaku. Bapak memang benar-benar rindu dengan anak-anaknya. Kulihat itu dari binar matanya yang berair dan melindap redup saat melihatku.
“Kamu pulang, Prayoga? Bapak sudah kangen”.
Aku hanya mengangguk dan masih tak bisa berkata apa-apa. Aku sendiri menjadi merasa jijik dengan bapak saat ini. Tangan bapak yang puluhan tahun lalu dipakai untuk menyuapiku dan adik-adik beberapa menit lalu digunakan untuk menyuapi mulut orang-orang gila?
Siapa sebenarnya yang tengah menjadi gila? Aku, orang-orang gila itu atau bapak?
Lek Muksin langsung pamit pulang dengan wajah pucat, sesaat kemudian kulihat orang-orang gila itu berhamburan. Beberapa dari mereka berjalan mendekatiku, membuat bulu kudukku berdiri, tersenyum lebar dengan gigi kuning pucat dan sisa-sisa nasi di mulutnya. Lantas merekapun satu-persatu menuju pintu dan keluar dengan tawa yang menggelegar, sebagian dengan tangis yang meraung-raung. Samar-samar kudengar suara mereka. Semakin jauh, semakin menyebarkan bau busuk dan aroma ketakutan. Sesaat kemudian kulihat bapak kembali ke meja makan, mengemasi sisa nasi yang tercecer dan memandang jauh keluar lewat celah jendela yang terbuka lebar.
“Mereka sudah pergi. Aku jadi harus makan siang sendirian. Kamu sudah makan Prayoga? Ayo, sini temani bapak makan”.
Kupaksakan kakiku melangkah menuju meja makan. Kugeret kursi dan kuhempaskan tubuhku di sana.
“Kenapa bapak membawa mereka ke rumah?” tanyaku
“Siapa? Orang-orang gila itu?” balas bapak bertanya padaku
“Iya to pak. Kenapa mereka ada di rumah kita dan makan dari tanganmu sendiri? Kenapa mereka datang kemari setiap hari?”
“Kenapa setiap pagi bapak pergi mencari orang-orang gila untuk kau cium tangan dan wajah sarat kenajisan itu?Lek Muksin telah menceritakan semuanya, pak. Apa itu amalan dari tarekat yang bapak jalani saat ini? Jika iya, segeralah bapak keluar dari ajaran itu. Itu sesat dan pimpinan tarekat itu pasti hanya orang gila yang sesat”. Tanyaku dengan rentetan tanda tanya yang seakan tak habis-habis dari benakku
Bapak hanya melirik, sesaat kemudian menghela nafas panjang.
“Kamu itu seperti Muksin dan orang-orang kampung saja yang selalu bertanya-tanya masalah orang gila itu. Kucium tangan mereka itu karena aku ingin menciuminya? Dan apakah itu salah? Aku juga tidak pernah memaksa orang-orang gila itu untuk datang ke rumah. Mereka datang-datang sendiri dan akupun tak mengerti. Kalo kamu mau tahu ya tanya saja sama mereka, jangan sama bapak”.
“Lantas kenapa bapak menerima mereka? Bahkan memberi mereka makan dan menyuapinya dengan tangan bapak sendiri?”
“Lho, kenapa bapak mesti menolak tamu-tamu bapak?” jawab dan tanya bapak sekaligus
“Mereka itu bukan tamu, pak. Mereka adalah orang gila!” jawabku
“Apa orang gila itu gak boleh jadi tamu? Siapa yang datang ke rumah ya itu tamu bapak kan? Dan apakah pantas bapak mesti makan sendiri sedang ada tamu yang duduk di rumah bapak?” tanya bapak
“Bapak! Mereka itu orang gila, pak!”
“Iya, mereka itu orang gila! Lantas kenapa?”
Jawaban-jawaban bapak semakin membuatku tak mengerti. Sejak dulu apa yang bapak lakukan memang kerap membuatku tak mengerti, dan kali ini lagi-lagi akupun dibuatnya tak mengerti dan tak tahu mesti berbuat apa lagi.
“Besok usir mereka semua, pak! Jangan ada orang gila yang masuk kampung apalagi rumah ini. Mereka hanya menebarkan bau busuk dan kutukan. Kedatangan mereka hanya membuat orang-orang kampung menjadi takut. Dan aku tak ingin mereka ada di sebelahmu. Mengisi rumah kita dengan kotoran dan kenajisan”. Pintaku kepada bapak dengan sedikit memaksa
“Oh, jadi bapak harus mengusir tamu-tamu bapak itu? Kembali bapak bertanya
Bapak menolehkan wajahnya ke wajahku. Sorot matanya yang semakin menajam benar-benar hampir membuatku buta.
“Jika tamu-tamu bapak atau di antara mereka itu adalah Kanjeng Nabi Khidir apakah bapak harus mengusirnya juga?” Tanya bapak setengah berbisik.
Pertanyaan bapak terakhir itu terasa benar-benar menyesakkan dada dan membuatku terbata-bata. Aku jadi yakin benar siapa di antara kami yang tengah menjadi gila.
“Khidir? Orang-orang gila? Apa hubungannya?” batinku
Ajaran tarekat yang ganjil itu pasti telah menyesatkan pikiran bapak. Pesantren dan ajaran tarekat memang kerap menyebarkan kesesatan yang ganjil dan takkan pernah bisa dipahami apalagi diyakini. Membuat pengikutnya menjadi seorang yang takhayul dan aneh. Bukan aku tak percaya tapi kerap cerita-cerita Kyai pesantren yang mistis dan takhayul tak patut untuk diimani. Tuhan sudah terlampau ganjil dan aku harus bersusah payah untuk benar-benar mengimaninya. Dan kali ini dongengan tentang Nabi Khidir pasti telah menyesatkan bapak.
“Khidir guru Musa itu? Apa mungkin masih ada to pak? Nabiyullah dengan jubah dan sorban hijau, berbau wangi sorga dan penuh kemuliaan itu adalah orang gila?” Tanyaku sekali lagi.
Bapak tak menjawab. Menghela nafas panjang, berdiri memandangku sejenak lantas berlalu pergi menuju kamar dan menutup pintunya. Helaan nafas dan segala yang diam itu adalah jawaban paling tepat dari bapak atas pertanyaan-pertanyanku. Dan aku sekali lagi tak mampu untuk benar-benar mengerti apa yang bapak inginkan.
Di bagian dinding kayu yang berlubang itu kucoba melihat-lihat apa yang tengah dilakukan bapak di dalam. Tapi bapak tak sedang berbuat apa-apa. Ia hanya duduk bersila, dalam hening dan memutar-mutar tasbihnya.
“Duh, Gusti! Apa bapak bener-bener telah menjadi gila?”
****************
Di Baitullah, di pelataran rumah Allah kuhaturkan segenap doa demi keselamatan dan kesejahteraan anak-anakku. Sebagai bapak itulah satu-satunya doa yang dapat kupanjatkan. Tapi jika untukku sendiri tak ada hal lain yang paling kurisaukan selain Khidir. Pertemuan dengan Khidir adalah satu-satunya harapan yang sudah kupendam sangat lama, jauh sebelum aku bertemu Kiryani yang akhirnya menjadi istriku dan melahirkan anak-anakku. Doa yang kusimpan sejak masih nyantri kepada almarhum Abah Fatoni di pesantren Al Hidayat puluhan tahun lalu.
Sejak bertahun-tahun menjadi santri sebenarnya aku tidak begitu dekat dengan Abah atau keluarga dalem.
Sekali dua kali memang beliau pernah memintaku mengantar beliau mengisi pengajian di kampung-kampung sebelah atau ke luar kota, tapi aku memang tak pernah bisa berkata-kata jika sudah berhadapan dengan beliau. Bagiku adalah pantang mengajak Kyai mengobrol sembarangan selain urusan agama. Aku hanya bisa nderek dawuh dan mengamalkan apa yang telah beliau ajarkan tanpa banyak bertanya. Beliau sendiripun adalah Kyai yang tenang dan jarang berbicara dengan santrinya kecuali saat mulang ngaji. Tapi aku tahu, sebenarnya beliau juga memperhatikanku. Itu baru benar-benar aku mengerti saat lulus dan khatam nyantri kepada beliau. Di dalem aku pamit pulang dan mungkin tidak lagi kembali ke pondok. Beliau dan Bu Nyai menerimaku dan langsung turut mendoakanku.
Tapi ada yang masih tak bisa ku mengerti bahkan sampai saat ini, setelah mendoakanku Abah menyuruhku mendekat kepadanya yang tengah duduk bersila di ruang tamu. Dengan sedikit memaksa abah menarik baju dan memegang pundakku. Beliau membisikkan sesuatu hal yang teramat ganjil dan tak pernah bisa aku lupakan.
“Carilah Nabi Khidir. Aku tidak bisa ngasih sangu apa-apa selain mendoakanmu semoga kaupun berjodoh dan memperoleh pertemuan dengan kanjeng Nabi Khidir”.
Sampai saat ini aku sendiri tak bisa mengerti apa maksud beliau dengan keinginannya itu. Aku hanya bisa mengangguk dan mengamini. Pesan Abah hanya mampu kusimpan dalam-dalam sampai saat ini.
Khidir? Nabiyullah yang Musa pun tak mampu mengikutinya? Bagaimana seorang bocah kampung yang cuma bisa ngaji dan macul sepertiku ini bertemu Nabi Khidir?
Ada apa Abah?
*********
Dan sepulang berhaji aku mengikuti sebuah pengajian tarekat yang dipimpin Habib Nuh, ulama sekaligus pimpinan salah satu pondok di kota ini. Sekedar pengisi hari-hari tuaku yang semakin menua. Bagiku hidup yang tinggal sejenak ini semoga menjadi waktu yang cukup bagiku menuju Tuhan, menuju kerahmatan yang selalu diidam-idamkan semua hambanya.
Suatu siang selesai pengajian tarekat kucoba untuk sowan ke rumah Habib. Saat itu para tamu sudah pulang dan dengan terbuka Habib Nuh menerima kedatanganku. Saat itu tak ada hal lain yang coba hendak kutanyakan selain amanat dari Abah yang belum kegenapi sampai sekarang mencari Sang Nabi Penjaga Lautan, sekaligus juga meminta doa sekiranya dalam masa hidupku ini Allah berkenan mempertemukanku dengannya, Nabi Khidir.
Habib tampak begitu terkejut atas apa yang kusampaikan. Seketika itu Ia berdiri, menengadahkan kedua tangannya dan berdoa mengharap apa yang menjadi keinginanku dapat segera terkabulkan. Selesai berdoa beliau menyuruhku untuk langsung pulang. Sebenarnya aku sendiri belum puas bertanya kepada Habib. Masih banyak hal yang ingin kudengar perihal Khidir dari mulut beliau. Tapi baru saja aku menyampaikan maksudku beliau langsung mendoakan dan menyuruhku pulang. Mau bagaimana lagi. Sebagai santri adalah pantang bagiku menanyakan dawuh Kyai. Maka aku hanya bisa pamit dan kulangkahkan kaki keluar dengan hati yang masih penuh tanda tanya.
Setelah berjalan cukup jauh meninggalkan pondok yang cukup luas itu, lapar tiba-tiba telah melilit perutku. Mungkin kelelahan sedang seharian akupun belum menelan apapun. Di seberang jalan jarak beberapa meter dari tempatku berdiri, tampak sebuah warung makan kecil yang sepi dan sepertinya baru saja dibuka. Aku berhenti di warung itu untuk makan dan sejenak beristirahat.
Di warung inilah keganjilan pertama terjadi dan tak akan bisa kulupakan seumur hidup. Setelah pesanan diantarkan dan aku siap menelan sesendok nasi, dari luar datang lelaki gila, berbaju hijau kotor tak bercelana, bau busuk dan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba saja dia masuk, menaiki meja makan, mengibaskan sendok nasi yang hampir kutelan, melumat nasi dipiringku dengan tanganya, meludahinya.
Aku tak tahu harus berbuat apa. Dengan penuh ketekutan kutatap benar wajah lelaki gila itu, wajahnya yang kotor belepotan lumpur dan kotoran, mulutnya menyerigai lebar mengerikan dan bau busuk tubuhnya menghilangkan rasa laparku seketika.
Tak hanya itu, orang gila itu beraksi kian menggila. Meloncati tempat sayur pemilik warung. Di acak-acak semua lauk pauk, diobok-obok panci sayur dengan tangannya yang kotor itu. Aku hanya mampu berdiri kaku, seperti dijerat benang-benang gaib yang kencang dan tak ada lagi yang dapat kulakukan.
Dari belakang warung, pemilik warung setengah berlari menuju depan. Membawa pisau dapur yang diacung-acungkan. Mengetahui pemilik warung datang dengan pisau yang terpegang erat di tangannya orang gila itu langsung meloncat dan berlari keluar dengan tertawa terbahak-bahak. Aku hanya bisa tertegun menatap warung yang telah berantakan, sampai suara makian pemilik sayur yang keras menyadarkanku seketika.
Ada apa dengan orang gila ini? batinku
Perasaan ganjil menghinggapai benakku. Kedatangannya tepat saat hampir kutelan makanan, mengacak semua benda yang ada di dalam. Maka bergegas kukejar orang gila itu keluar. Tapi baru sampai di depan warung lagi-lagi aku harus dikejutkan oleh penglihatanku sendiri. Sangat ganjil. Di depan sudah tidak ada siapa-siapa, hanya jalanan lengang, padahal hanya selang beberapa detik saja aku coba mengejarnya. Kuperiksa jalan, tak ada gang atau jalan pintas. Hanya aku dan pemilik warung yang juga tampak terheran-heran.
Kasihan juga pemilik warung makan yang sepi itu. Baru saja makanan-makanan dagangannya siap disajikan tapi sudah acak-acak oleh orang gila dan tentu saja sudah tidak bisa dimakan. Dengan beberapa lembar uang puluhan ribu yang kubawa dari rumah untuk jaga-jaga kuberikan semuanya kepada pemilik warung.
Karena peristiwa ini tampak aneh bagiku maka kuputuskan kembali ke pondok Habib Nuh. Di rumah dalem Habib menemuiku lagi dan bertanya kenapa baru sebentar aku sudah kembali. Kuceritakan semua yang telah terjadi sepeninggalku dari pondok.
Habib mendengarkan cerita yang kuejakan perlahan-lahan, ia terdiam sejenak lantas tersenyum kecil.
“Pak Kaji Marjuki, sampeyan tadikan minta di doakan supaya dapat ketemu Kanjeng Nabi Khidir. Alhamdulillah doa itu dikabulkan. Kalo saja Pak Kaji tahu, sejatinya orang gila itu tadi adalah beliau Kanjeng Nabi Khidir, orang yang sampean cari sejak puluhan tahun lalu”.
Jawaban Habib Nuh itu benar-benar membuatku terperanjat.
“Orang gila tadi Nabi Khidir ya Habib?”
“Mana mungkin seorang Nabi itu adalah orang gila?” sanggahku
Habib hanya tertawa saja mendengar pertanyaanku.
“Siapapun takkan ada yang tahu siapa sesungguhnya Nabi Khidir. Dan bebas saja Nabi Khidir merubah dirinya menjadi apapun bahkan menjadi orang gila sekalipun saat menemui seseorang. Sah-sah saja kan Pak Kaji?”
“Kalo sampeyan gak percaya juga gak papa. Untuk masalah keyakinan yang ganjil seperti ini kita memang harus lebih hati-hati”. Jawab Habib Nuh
Aku hanya terduduk dan tak tahu berbuat apa. Gambar wajah orang gila itu melesap cepat ke dalam kepalaku menyesakkan rongga-rongga dadaku.
“Tapi Habib, ingin juga saya dapat berguru kepada beliau, Kanjeng Nabi Khidir”. Ucapku dengan terbata-bata.
“Lho sampeyan kan cuma minta doa supaya Allah berkenan memberi kesempatan bagi sampeyan untuk bisa bertemu sama Nabi Khidir. Lha itu sudah dikabulkan. Bersyukurlah Pak Kaji, itu sudah cukup. Tak setiap orang dapat ketemu sama beliau. Kalo meminta lebih namanya tarak alias serakah.”
Aku masih tak bisa berfikir apa-apa. Sampai terlumat segala detak di dadaku yang semakin melambat lalu kembali teratur seperti suara arloji, berdetik-detik. Aku masih tak ingin bersepakat pada setiap peristiwa. Pada pertemuanku dengan Khidir yang sekejap setelah berpuluh-puluh tahun aku menunggunya.
Masih kuhapal betul wajah itu, wajah kotor belepotan lumpur dan kotoran, mulutnya menyerigai lebar mengerikan dan bau busuk tubuhnya adalah bau paling busuk sampah-sampah manusia yang dibuang, dipinggirkan. Tubuh orang-orang beraroma kutukan.
Sejak itulah ceritaku dengan orang-orang gila di mulai. dengan orang-orang yang di anggap tak waras, di singkirkan jauh di sudut-sudut peradaban manusia, dan aku jadi mengerti benar siapa-siapa sebenarnya yang menjadi gila, siapa-siapa yang patut dihargai dan diterima.
Aku memang telah menjadi gila.
**************
Pagi itu, terasa benar gelegar halilintar bergelegar keras di dadaku. Wajahku adalah wajah langit yang pucat. Setelah hampir dua bulan sejak pertemuanku dengan bapak, sekali lagi Lek Muksin datang ke rumah. Dengan tubuh berkeringat dan raut wajahnya yang pucat dia mulai menyampaikan maksud kedatangannya dengan perlahan-lahan. Tampak ragu untuk berkata.
“Mas Prayoga, saya harap mas bisa pulang. Anu mas, Mbah Kaji terpeleset sehabis solat subuh berjamaah di mushola dan tak sadarkan diri sampai sekarang”. Ucap Lek Muksin terbata-bata.
Sontak kecemasan merimbun cepat dalam otakku. Aku tersentak, berharap berita tentang bapak yang kesekian di bawa Lek Muksin hanyalah seduah dagelan. Serasa gelap benar pandanganku seketika itu. Telingaku berdenging keras dan udara terasa begitu senyap.
“Apa Lek?! Bapak jatuh?”
Maka langsung saja kuambil kunci mobil menuju keluar rumah. Lek Muksin mengikutiku dengan tergesa. Pintu dan pagar rumah kukunci rapat. Mobil yang telah terparkir di luar sejak semalam segera kunyalakan.
Belum sampai kutancap gas, di kaca mobil tampak lintasan bayang-bayang bapak merayap perlahan. Kulihat wajah bapak yang gembira dengan mata yang berair melindap redup saat terakhir dia melihatku. Bayangan wajahnya yang kurus dan terduduk hening di lantai kamar dengan memutar-mutar tasbihnya, lalu berganti wajah orang-orang gila dengan sisa-sisa nasi di mulutnya. Lamunanku benar-benar terbawa saat terakhir di rumah bapak. Sampai akhirnya sebuah tepukan cukup keras dipundak dan wajah Lek Muksin yang heran sambil bertanya kenapa membuatku benar-benar tersadar.
Mobil segera saja kupacu menuju pulang ke kampung, ke rumah pertama yang kumiliki, tempat bapak mengenalkanku pada Tuhan, pada agama dan bau sawah yang ranum yang menghidupi kami sejak kecil sampai sekarang kami dapat dibilang mapan, juga kenangan-kenangan pada almarhum ibu yang meninggal saat melahirkan Laksmi, adik bungsu.
Jalanan kota telah mulai padat. Tampak cukup jauh di tepi seberang jalan orang-orang gila bergerumul. Sebagian mereka adalah orang-orang gila yang waktu itu kutemui di rumah bapak, sebagian lain tak kukenali. Kini kecemasan bercampur rasa takut datang saat melihat mereka.
Sejam lebih kutempuh jalanan pedesaan berbatu, akhirnya sampai juga di depan rumah bapak. Para tetangga sudah ramai di luar atapun di dalam rumah. Kedatanganku tampak membuat mereka lega.
Tampak tubuh gemuk Budhe Narti setengah berlari menghampiriku.
“Oalah nang, akhirnya kamu pulang. Sejam tadi Pak Kaji siuman. Dia memanggil-manggil namamu”.
Aku tak menjawab segera berlari menuju dalam rumah. Selintas mataku melihat orang-orang.sekitar. Tak ada orang gila dan itu membuatku lega. Di dalam sudah banyak orang, di dalam kamar bapak sudah ada beberapa orang tetangga. Mereka satu persatu keluar dari kamar saat melihatku telah ada di depan pintu.
Di antas ranjang, telah tergeletak tubuh kering bapak. Wajahnya pucat sepucat langit pagi itu, sepucat wajahku. Kuraih tubuh bapak, kueja helaan nafasnya, masih terasa ada sisa nafas yang perlahan-lahan berhembus. Aku sedikit tenang. Kupanggil Lek Muksin. Dengan cepat dia sudah datang.
“Lek tolong bantu saya mengangkat bapak. Ayo kita bawa ke Rumah Sakit saja”.
Baru saja aku selesai berkata, sesuatu yang dingin, basah dan gemetaran memegang lenganku. Kupalingkan wajah dan kulihat bapak telah siuman, meraih tubuhku dan berusaha bangun. Sontak kupengang tubuh bapak dan membaringkannya kembali.
“Bapak? bapak sudah sadar? Sudah bapak tiduran saja. Biar nanti saya dan Lek Muksin yang bantu mengangkat bapak keluar. Kita bawa bapak ke Rumah Sakit biar bapak cepet-cepet di tangani dokter”.
Bapak menolehkan wajahnya ke wajahku. Kulihat kembali mata yang berair itu yang semakin lindap dan meredup dari dua bulan yang lalu.
“Buat apa?” Jawab bapak yang lagi-lagi membuatku tertegun.
“Bapak sudah gak apa-apa, nang. Syukur kamu cepet-cepet pulang. Bapak sudah kangen”.
Lek Muksin masih berdiri kaku di depan pintu. Kulihat wajahnya pun meredup kusut dengan mata memerah. Sesat kemudian tangan bapak sudah ada di pundak dan menarikku perlahan. Aku berbalik, bapak segera mendekatkan wajahnya ke sisi wajahku. Membisikkan sesuatu hal yang tak pernah aku mengerti.
“Jika kau mampu nang, carilah Khidir. Aku gak bisa ngasih sangu apa-apa selain doa atas kesejahteraanmu dan adik-adikmu, juga semoga kaupun kelak dan dapat bertemu Kanjeng Nabi Khidir. Bapak telah ditemuinya dalam wujud paling indah dan bapak jadi mengerti benar siapa-siapa saja yang sebenarnya orang mulia. Dan itu bukan kita”.
Ucapan bapak lagi-lagi membuatku tercengang. Sejak dulu apa yang ia kerjakan tak mampu sepenuhnya kumengerti. Dan kali ini ia memintaku mencari Khidir? Riwayat semacam dongengan itu? Apa ia memang ada? Kalaupun memang ada, apa Khidir sampai sekarangpun masih ada? Kau telah menemuinya Pak? Ada apa dengan Khidir? Ada apa antara pertemuanmu dengannya?
Berbagai pertanyaan tumbuh sangat cepat di kepalaku. Tapi dalam keadaan seperti ini aku tak bisa memaksakan apapun kepada bapak. Aku hanya mengangguk dan mengiyakan.
“Injih, pak”
Kulihat lagi Lek Muksin. Kuberi isyarat agar dia segera mendekat dan segera membantuku mengangkat tubuh bapak. Tapi belum sampai Lek Muksin mendekat tiba-tiba ranjang bapak seperti bergerak. Ada yang terhempas. Aku segera berbalik dan tubuh bapak yang dari tadi berusaha keras meraih tubuhku kini terhempas kembali ke ranjang.
Aku membatu dan semakin membatu. Telingaku kembali berdenging kencang. Seisi kamar tampak menjadi gelap, detak di dadaku berguguran. Kulihat lagi wajah bapak, cahaya di sekitaran wajahnya benar-benar melindap dan tiada. Kuraih dadanya, tak ada suara apapun, tak juga detak jantung bapak, hanya suara denging telingaku yang berdesing-desing.
“Bapak mangkat”. Ucapku lirih, tak sadar dan seakan masih tak percaya.
Lek Muksin dan tetangga-tetangga sontak segera menuju ke dalam. Sebagian memegangi tubuhku yang melemas. Sebagian memeriksa tubuh bapak.
Bayangan bapak saat menyuapi orang-orang gila kembali terlintas. Bayang tubuh layu yang dalam duduk hening memutar tasbihnya dan suasana saat ini kurasa benar-benar hening.
Belum juga aku menyadari apa yang sepenuhnya berlaku, sayup-sayup dalam jarak yang jauh kudengar suara-suara orang menangis, meraung-raung. Semakin lama suara-suara tangis itu semakin dekat dan terus mendekat.
Tiba-tiba para ibu dan tetangga yang ada di luar rumah menjerit dan setengah berlari masuk ke dalam. Suasana di kamar bapak kembali riuh. Orang-orang di luar sudah pada ribut.
“Ada orang gila! Ada orang gila!!”.
Sontak aku, Lek Muksin dan para tetangga lain menuju ke luar. Barisan orang-orang gila berpuluh-puluh datang. Mereka datang dengan suara tangis yang menyayat tak tertahankan. Seperti sepasukan sepi yang tak pernah istirah menyergap kami yang ketakutan. Sebagian kecil dari mereka adalah yang kulihat di jalanan kota tadi.
Lek Muksin dan beberapa tetangga segera mengambil pentungan, arit, pacul, batu dan apapun benda keras di sekitaran. Diacung-acungkan ke arah gerombolan orang gila. Lek Muksin dengan keras mengangkat suara.
“Edyan. Minggat pora?! Kono minggat!!”
Disusul suara para lelaki lain. Sebagian sudah melemparkan batu-batu ke arah kerumunan orang-orang gila itu. Tapi orang-orang gila itu terus mendekat dan tak peduli pada hujan batu yang menghujam ke kepala dan tubuh mereka. Tangis mereka melingking melebihi teriakan ketakutan kami.
Dadaku semakin sesak dan penuh dengan tangis orang-orang gila yang meraung-raung.
“Orang-orang gila itu datang tepat saat bapak menghembuskan nafas terakhirnya?
Apa lagi ini Gusti”. Batinku yang masih tak mengerti tentang keganjilan semacam apa lagi yang terjadi.
Para tetangga masih berusaha melempar batu, mengacungkan pentungan, memegang erat sabit yang siap dilesatkan ke leher orang-orang gila itu.
Kubayangkan darah orang-orang gila mengucur deras dari leher-leher mereka. menggenangi kampung, menggenangi halaman rumah bapak, menggenangi jasad bapak.
“Tidak...!! Sudah! Sudah!! Jangan lempar lagi. Biarkan saja mereka datang, pastinya hendak melayat kepulangan seorang lelaki yang telah berbulan-bulan merawat dan menghidupi mereka”. Pintaku ke para tetangga
Orang-orang tercengang, melihatku dengan keheranan, menurunkan benda-benda di tangannya. Suasana kembali tenang. Hanya suara-suara tangis yang melengking tajam juga sesenggukan tangis dari kami yang hampir tenggelam.
Orang-orang gila itu telah sampai di rumah. Kami hanya membatu, melihat mereka, menyaksikan kegaiban menjalin tubuh kami dan tubuh orang-orang gila menjadi satu. Mereka telah mengisi pekarangan, sebagian lain telah ada di dalam rumah. Dengan tangis yang menyayat. Dengan air mata yang tak putus-putus.
Hari itu kami semua menjadi saksi keganjilan yang benar-benar tak bisa kami mengerti. Bagaimana bisa orang-orang gila se-kota datang ke rumah bapak dengan tangis dan air mata tepat saat bapak menghembuskan nafas terakhirnya?
Mereka ikut menunggui jenasah bapak dimandikan, menangis meronta-ronta saat jenasah bapak disholatkan, dari belakang mereka turut mengantar jasad bapak menuju ke pemakaman. Tak hanya itu, merekapun menunggui jenasah bapak dikuburkan dan tetap bertahan di sana sekalipun orang-orang waras lainnya sudah pergi.
Mereka benar-benar seperti barisan kesedihan yang menyergap kesadaran semua orang yang melihatnya. Sebagian dari kami bergidik ketakutan, sebagian lain turut menangis. Yah, sepertiku dan beberapa orang lain. Kami menangis bersama-sama dengan orang-orang gila entah atas apa?
Atas kematian bapak yang teramat ganjil ini, pada diri kami sendiri ataukah karena orang-orang gila ini telah membuat kami terus-menerus bertanya, siapa diantar kami sebenarnya yang telah menjadi gila?
**********************
Kini sudah genap tujuh hari orang-orang gila itu berada di makam dengan kesedihan yang melebur dengan suasana sunyi pemakaman. Prayoga tampak melihat di ujung makam paling sepi, di bawah pohon kamboja. Menyaksikan kegilaan yang teramat ganjil. Menyaksikan perhelatan suci orang-orang gila.
Bahkan saat daun-daun kamboja itu tanggal karena angin serupa golok yang mengibaskan tubuhnya tak tentu arah, juga beberapa kembang kamboja putih jatuh di bahu Prayoga, seperti hendak memutus tatapan lelaki itu yang terus menajam. Tapi tubuh kekar itu telanjur kaku dan ia benar-benar tak tahu.
Pohon-pohon bambu berderit seperti jerit yang tak lelah menjaga isi pemakaman, yang menyadarkan peziarah, inilah dunia asing dari dunia luar yang bising tak karuan, yang hanya ada sepi dan kesedihan telah dikubur dalam-dalam. Tapi Prayoga masih saja tak bergeming dari tempatnya berdiri.
Yah, barangkali dia memang tak perduli. Saat ini dia hanya berfikir dan benar-benar ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di depan matanya.
Orang-orang gila itu, kenapa mereka menangis?
Orang gila memang suka menangis tiba-tiba, tertawa tiba-tiba. Tapi ini? Orang-orang gila sekota menangis meraung-raung di kuburan Kaji Marjuki sejak pertama sampai sekarang genap seminggu beliau dimakamkan?
“Dasar gila!”
“Ini apa?” Batinnya.
“Ini kewajaran prayoga” ada sesuatu yang berbisik di telinga Prayoga
Seketika itu Prayoga berbalik. Di depannya, jarak sejengkal dari wajahnya, seorang lelaki berbaju hijau kotor, tak bercelana dan orang-orang pasti tahu bahwa orang ini pasti orang gila. Menjawab keresahan batin yang menyergap Prayoga. Prayoga hanya tertegun melihat lelaki gila ini tiba-tiba tertawa terbahak-bahak.
Wajahnya kotor belepotan lumpur dan kotoran, Giginya kuning gading, bau busuk tubuh yang menyengat, yang tak ada wewanginan apapun selain tubuh keringat manusia bercampur bau sampah paling busuk beraroma kutukan.
“Ini hanya kewajaran saja. Dan bapakmu telah mengenal Khidir yang sederhana saja”. Ucap lelaki itu setengah berbisik setengah tertawa.
Prayoga tertegun, tubuhnya gemetaran. Ia langsung merebut tangan lelaki itu, yang kotor dan penuh dengan kenajisan. Di pegang erat tangan dan diciuminya. Prayoga sendiri tak mengerti pada apa yang telah dilakukannya. Tak ada alasan yang cukup mengapa ia mencecap tangan itu. Ia lelah berpikir keras tapi tetap tak mengerti. Ia hanya ingin menciumi tangan itu seperti yang pernah dilakukan bapaknya, Kaji Marjuki.
Sampai ia benar-benar tersadar, saat kesekian kalinya ia genggam dan ia ciumi tangan busuk lelaki gila itu, ibu jari tangan kanan lelaki gila itu tak bertulang. Yah, ibu jari tangan lelaki itu benar-benar tak bertulang*.
Seketika persendian kaki Prayoga lemas, melemas juga persendian lainnya. Ia terjatuh, mengangis meraung-raung, seperti tangis para orang gila entah atas sebab apa.
Semarang, 26 April 2010 / 30 November 2010
*Sebagian para pelaku Thareqat dan Tasawwuf terutama di Indonesia percaya bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang ini. Beliau terkadang datang mendatangi seseorang sebagai pintu bertambahnya tingkatan/maqom derajat seseorang Waliyullah. Beberapa catatan yang beredar mengatakan bahwa belaiu bercirikan ibu jari tangannya tak bertulang.
** Cerpen ini masuk sebagai juara I Lomba Cipta Sastra II Undip dan masuk dalam antologi buku "Kota dan Orang-Orang Gila"





 RSS Feed (xml)
RSS Feed (xml)