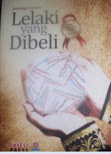Ada yang berdenging sampai bising. Sampai kabut teramat sepi, dan perabot-perabot rumah seperti memaki.
"Selamat usang seperti kami!"
Lalu lampu-lampu melebarkan bayang tubuhmu. Merayapi dinding sampai gelisahmu benar-benar tak tentu. Ini yang purba sejak luka tak lagi dari nganga, yang kerap datang saat pancaroba. Merayap di garis pecah tapak kaki. Lalu hujan juga dadamu itu.
Rumah ini tempat memampatkan segala yang terkucur dari di telapak tangan. Asin dan membasahi gaun merah yang membalut tubuhmu. Dan malam berdetak semakin kencang melemparkan sabit yang teramat nyata. Gerak arloji yang melambat dan jantungmu seperti tertahan semakin pelan.
Kau seperti lelah terduduk di depan kaca. Membersihkan wajah yang belang, sisa-sisa bedak sesore yang surup tadi. Lipstik yang belepotan dan bibirmu jelas berkerut, pucat pasi. Tapi, bayang-bayangmu tak memperlihatkan apa-apa. Tak menunjuk dirimu atau tubuh yang mengendur otot-ototnya.
"Kita milik siapa sebenarnya? Jika waktu memang tak pernah punya pintu. Tak melempar atau menarik tubuhmu. Pada ranah yang tak sepenuhnya nyata."
Kau hanya terduduk dan melepas resah di sudut meja.
“Aku tak pernah memulai apapun. Maka tak ada yang harus kuakhiri.”
“Seperti sajak ini?” tanyaku subuh itu.
Barangkali, dan aku lelah menjadi pendosa hanya karena bertanya tentang “kenapa?” dan “bagaimana?”.
“Sesekali aku ingin membenci Tuhan. Tapi aku terlampau takut.”
Gelap yang larut dan air matamu yang turut mengendap bersama-sama dengan ampas kopi. Sayap malam yang tanggal saat kepul rokokmu terlempar seperti mengabarkan hidup memang sial. Tapi apalah itu, jika kau masih tak ingin memejamkan matamu barang sekali.
Atap-atap yang merunduk dan saat kau sadari bahwa apapun yang terjadi saat ini kau mulai hampir tak perduli. Kamu mulai mencair, lumer dan menjadi genangan di rumahmu sendiri. Bahkan sebelum Langit memberi pagi dengan kepul asap di tungku dapurmu. Kau sudah benar-benar luruh.
“Aku selalu mencintai subuh, tapi tidak pagi. Karena bunyi-bunyian dari ranting dan burung-burung kerap membuatku alpa.”
Maka kubiarkan saja kau terjaga. Mengawasi langit-langit kamarmu dengan curiga. Saat laba-laba merayap cepat dengan jaring-jaring gaib yang mulai menutupi ranjang dan menjalin tubuhmu menjadi semacam debu. Kau masih berpura-pura waspada.
Saat itu aku akan kembali menyusup. Melewati lubang mulut, hidung, telinga atau bahkan pori-pori kulitmu. Saat itu aku akan memaksamu terpejam. Melupakan setiap peristiwa. Menerbangkanmu ke langit sebagai wanita berbibir senja, hangat dan menggetarkan, melempar api dan kutuk di sudut-sudut kota.
Lalu saat kau kembali tersadar, kau harus memulai lagi hidup lebih awal dengan segala kemalangan baru, rindu yang sial dan segala tanda tanya. Sedang kau semakin kehabisan waktu.
Semarang, 22/04/2010
Asal-Usul Keranda Mayat dan Kisah Putri Rasulullah SAW
18 jam yang lalu





 RSS Feed (xml)
RSS Feed (xml)